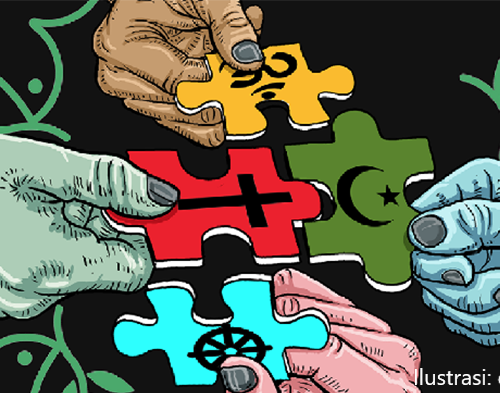Kurang lebih semenjak Hari Raya Idul Fitri 1442 H sampai saat ini, terjadi lonjakan Covid-19 yang luar biasa. Hampir semua belahan bumi Indonesia mengalami dampaknya. Korban semakin banyak dan berita tentang orang meninggal setiap hari lalu lalang tak terbendung.
Hampir di semua grup Whatsapp yang saya ikuti, setiap hari selalu saja ada berita orang meninggal. Mulai dari teman, orang tua, sanak saudara sampai dengan beberapa ulama dan kiai sepuh ternama. Mereka tutup usia sebagian besar karena corona.
Ungkapan kesedihan pun seperti tak terbendung. Sebab negeri ini masih butuh sosok kiai khos yang arif dan menentramkan hati. Namun ada aspek tak kalah penting selain ungkapan belasungkawa dan kesedihan yang mungkin luput selama ini.
Lantas, apa yang seharusnya kita lakukan dari sekadar share berita wafatnya para kiai “sepuh” setiap hari? Saya kira hari ini pertanyaan tersebut mendesak diajukan. Karena wafatnya kiai “sepuh” bagi umat bisa berarti kehilangan banyak hal. Bukan sekadar kehilangan sosok, melainkan umat kehilangan kapital intelektual, sumber keilmuan, sumber spiritualitas, sumber keteladanan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, fenomena ini merupakan “alarm” betapa kaderisasi ulama dari pesantren harus semakin diperhatikan.
Sebab terminologi kiai “sepuh” sebenarnya tidak hanya mengacu pada umur melainkan “jangkep”-nya berbagai ilmu kehidupan karena kematangan intelektual dan spiritual. Singkatnya, banyak orang “sepuh” secara umur tapi belum tentu “sepuh” dalam ilmunya. Tentu saja untuk mencapai maqam “sepuh” itu dibutuhkan proses dan tempaan yang panjang.
Sehingga sudah seharusnya, wafatnya seorang kiai menjadi peringatan keras bahwa proses kaderisasi harus segera berlanjut. Kaderisasi santri yang mandek menyebabkan tidak hanya pondok pesantren namun bangsa ini bisa gulung tikar. Mengingat peran besar kiai dalam upaya menanam semangat cinta Tanah Air dalam satu tarikan napas dengan perjuangan agama (Sumantri, 1994: 21).
Maka perlu upaya mencetak kader yang siap menggantikan estafet tanggung jawab keumatan. Dalam hal ini, saya jadi eling ungkapan Karel A. Steenbrink yang menyebut “pesantren” dengan istilah “priesterscholen” atau sekolah calon kader “pastor Islam” (Karel A. Steenbrink, 2007: 56). Pesantren seperti menjadi “badan” resmi pusat kaderisasi kiai.
Celakanya, kaderisasi kiai tidak bisa sesingkat membuat mie instan. Idealnya penggemblengan tersebut dimulai sedini mungkin dan bersifat continue. Tidak hanya gemblengan dzahiriah, tapi juga batiniah.
Dalam aspek dzahiriah seorang calon kiai harus menguasai berbagai keilmuan Islam seperti ilmu al-Qur’an, hadis, fikih, tauhid, nahwu, shorof, balagoh, dan lainnya. Itupun masih harus ditunjang dengan paradigma tasawuf agar seorang kiai tidak hanya “pinter dongeng, nulis lan moco.”
Adapun secara batiniah juga harus ditempa dengan berbagai tahapan riyadhoh, mujahadah dan komitmen mewakafkan sepanjang hidupnya untuk kepentingan umat. Tentu saja proses kaderisasi ini tidak mudah apalagi hari ini proses kaderisasi kiai terbentur oleh dua tantangan.
Pertama, banyaknya dzuriyah ataupun santri yang tersedot hiruk-pikuk kehidupan politik, daripada tekun mendidik santri yang jauh dari sorot kamera. Sulit untuk tidak beranggapan bahwa hari ini pesantren “bersih” dari tarik ulur kepentingan politik.
Fenomena politik masuk pesantren, secara tidak langsung turut membentuk proses kaderisasi politikus pesantren. Memang aktivitas politik ini tidak selalu berdampak negatif, tapi soal skala representasi, apakah klaim politik santri merepresentasikan kepentingan umat, diri sendiri atau partai politik? Yang jelas itu semua menjadi saling berjalin kelindan. Belum lagi persoalan teknis lainnya.
Bagi saya pribadi, fenomena politisasi pesantren dan pesantren yang politis menjadi suatu hal yang agak mengganjal hati. Meskipun juga tak ada larangan baik struktural maupun kultural. Namun menurut saya, seorang kiai harus (sedikit) menjaga jarak dengan kekuasaan. Sebab ia adalah “pamong”; guru dan pengasuh umat yang secara laku harus benar-benar bersih, sebagaimana laku kiai “sepuh.”
Sudah seharusnya wafatnya seorang kiai menjadi peringatan keras bahwa proses kaderisasi harus segera berlanjut. Kaderisasi santri yang mandek menyebabkan tidak hanya pondok pesantren namun bangsa ini bisa gulung tikar.
Kedua, lahir dari pribadi calon kader utama, yaitu para putra kiai atau sering dipanggil dengan sebutan “gus.” Dalam beberapa kasus, alih-alih menempa diri dengan serius, mereka justru menggunakan privilege nasab-nya untuk mengakses kemudahan-kemudahan dalam proses belajar. Hal ini seperti bom waktu, sangat berbahaya untuk keberlangsungan pondok pesantren di masa mendatang. Sebab kalau dibiarkan akan lahir generasi cengeng yang secara kualitas tidak sebanding dengan pendahulunya.
Maka untuk kaderisasi kiai bisa dimulai dengan meminimalisir intervensi politik praktis masuk pesantren dan memberantas nalar “kemegus.” Kemudian kembali fokus belajar mengajar dengan sungguh-sungguh, puncaknya khidmat umat sebagaimana laku para kiai “sepuh” yang telah wafat hari hari ini.
Terakhir, untuk menjaga kewarasan mental dan imunitas di tengah gelombang Covid-19, mari bersama-sama meletakkan gawai kita. Berhenti membaca berita corona dan men-share berita kematian setiap harinya. Cukup kita menjaga diri sebaik-baiknya, berdoa untuk keselamatan diri, keluarga dan saudara kita semua. Dan jangan lupa, life must go on, kita harus tetap menebar optimisme sembari mempersiapkan generasi penerus selanjutnya. Saya kira, itu lebih baik dari sekadar share berita corona. []