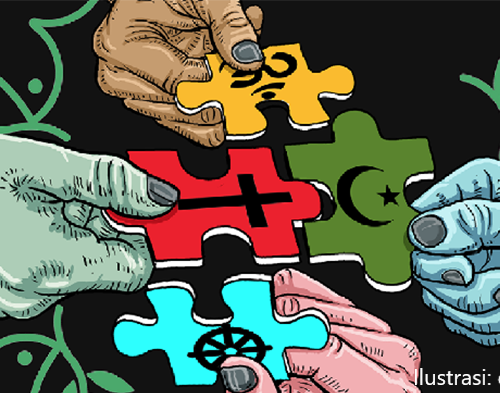Bagi generasi Y yang lahir dan tumbuh di pedesaaan seperti saya, masuk supermarket atau toko-toko retail modern adalah sebuah kemewahan.
Sebab saat kecil, orang tua saya hanya mengenalkan pasar tradisional dan toko kelontong sekitar tempat tinggal jika ingin belanja kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi tak terbesit sedikitpun untuk berani menginjakkan kaki di supermarket yang ber-AC dan menjulang tinggi.
Namun fenomena demikian tak berlaku lagi sekarang. Hanya dengan menginjakkan kaki beberapa ratus meter dari rumah saja, kita sudah bisa menemui minimarket mewah yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari secara lengkap.
Awal kemunculannya dulu, gerai minimarket waralaba itu hanya berada di jalur-jalur kota atau jalan provinsi. Asumsinya kehadiran mereka untuk melayani para pelancong yang melintas di jalan tersebut. Terutama para pelancong jarak jauh yang butuh toko modern “serba ada” dan mudah diakses dari jalan raya.
Namun belakangan, strategi itu tampaknya mulai sedikit diubah. Persaingan antar pengusaha yang semakin ketat dan perubahan perilaku konsumen, menarik mereka untuk menyasar desa-desa; wilayah perkampungan yang dulu tak pernah dilirik sebagai daerah potensial.
Kenapa kampung dianggap sebagai sasaran empuk untuk menawarkan barang yang pangsanya adalah kelas menengah dan kaum urban?
Pergeseran Budaya: Konvensional ke Digital
Barangkali ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan serius para pengusaha minimarket waralaba mengubah strategi bisnisnya dari kota ke desa.
Taruhlah misal perputaran uang di desa-desa sekarang semakin besar karena mereka sedang berlomba-lomba mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan kampung wisata sebagai contohnya.
Namun apakah analisa semacam itu cukup kuat dijadikan alasan untuk membangun imperium bisnis di daerah perkampungan yang relatif lebih sepi ketimbang kota? Saya rasa tidak!
Dalam sudut pandang lain, salah satu alasan kuatnya adalah pergeseran budaya dan perilaku konsumen. Lebih tepatnya adalah pergeseran dari budaya yang tadinya konvensional ke digital. Implikasinya tanpa disadari muncul budaya konsumtif.
Tentu saja hal ini bukan hanya faktor tunggal. Pengaruh iklan di media sosial dan gaya hidup menjadi bagian yang tak terpisahkan. Ya, revolusi digital memang menyuguhkan kemudahan dalam banyak hal. Daya tawarnya adalah perihal yang berbau “praktis.”
Padahal tidak selalu hal ihwal “praktis” itu membawa kemudahan dan memuaskan. Bukankah tak jarang orang tertipu saat membeli barang via online hanya karena label harga murah?
Fenomena aplikasi tatap muka virtual macam Google Meet atau Zoom juga bisa jadi contoh lainnya.
Di satu sisi, aplikasi itu membantu manusia melipat jarak dan waktu. Namun di sisi lain, ketika dunia kembali normal, pembelajaran atau pertemuan via daring tetap dirasa kurang maksimal.
Sebab ada feel yang tak mampu digantikan oleh teknologi dan hanya bisa “diobati” dengan kehadiran (presence) eksistensi manusia seutuhnya di dunia nyata.
Apalagi manusia kekinian yang telah berevolusi dari homo sapiens ke homo digitalis sesungguhnya tidak benar-benar merdeka atas dirinya.
Manusia—kata Hardiman (2021)—telah kehilangan subyek atas dirinya karena sumber pikirannya bukan lagi subyek melainkan pesan (message) dalam komunikasi digital.
Jika luapan informasi (information spillover) digital itu tak mampu disaring maka distingsi antara yang realitas dan fiksi sulit untuk dimaknai.
Konsumerisme dan Kelas Menengah Muslim
Nilai ataupun norma budaya ikut memengaruhi perilaku konsumsi. Sehingga budaya digital seperti sekarang, ikut serta berperan mendorong perilaku konsumtif sebagai tanda status sosial-ekonomi seseorang.
Tak hanya itu saja, aspek sosiologis, struktur dan interaksi sosial ternyata juga ikut andil dalam memengaruhi pola konsumsi.
Thorstein Veblen (1857-1929), seorang ekonom cum sosiolog Amerika, menyebut hal demikian dengan istilah “pemborosan demonstratif” dan “konsumsi simbolis” yang menjadi dasar bagi pemahaman budaya konsumerisme.
Senada dengan di atas, Jean Baudrillard (1929–2007) dalam salah satu karyanya yang popular, The Consumer Society: Myths and Structures juga memberikan argumentasi yang tak kalah menohok.
Baudrillard mengatakan bahwa konsumerisme dalam masyarakat kontemporer telah menjadi aspek fundamental dalam pembentukan identitas individu dan juga sosial. Lalu identitas apa yang ingin dibangun?
“Padahal kalau diamati dengan saksama, menjamurnya minimarket waralaba di desa-desa merupakan alarm bahaya bagi warung dan toko kecil (tentangga) kita.”
Asumsi saya, identitas tersebut merujuk pada (keinginan) labeling sebagai kelas menengah. Sebab kelas menengah Muslim terutama, telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam dinamika masyarakat Indonesia kontemporer.
Mereka muncul tak hanya sebagai peneguh simbol-simbol keagamaan, tetapi juga kelas sosial-ekonomi baru yang salah satu cirinya mengawinkan unsur “syariatisasi” dan “neo-kapitalisme.”
Mereka memilik akses pendidikan yang memadai, ekonomi yang stabil sembari tetap memegang nilai-nilai agama. Pun di sisi lain, mereka juga tak bisa lepas dari jerat gaya hidup yang dipengaruhi oleh tren global yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Islam.
Dalam istilah lain, kelas menengah Muslim memiliki peran yang kompleks dalam budaya konsumerisme; faktor-faktor ekonomi, sosial, dan budaya bersama-sama membentuk pola konsumsi dan perilaku mereka.
Lantas apakah perilaku tersebut setali tiga uang dengan peningkatan pendapatan masyarakat kita pada umumnya?
Mari kita lihat data pendapatan perkapita Indonesia dalam satu tahun terakhir. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.892,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp75,0 juta.
Namun secara umum, ekonomi Indonesia tahun 2023 hanya tumbuh sebesar 5,05 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen.
Dalam skala Asia, posisi Indonesia juga masih berada di bawah Thailand, Malaysia, Brunei Darrusalam, dan Singapura. Indonesia berada di posisi kelima dalam hierarki PDB per kapita pada tahun 2022 (https://databoks.katadata.co.id/).
Sayangnya saya tidak punya akses untuk melihat lebih jauh data real pendapatan per kapita di Jawa Timur dan lebih spesifik Tulungagung pada tahun 2023. Sebab di laman BPS, data tersebut tidak tersedia.
Namun yang pasti, secara persentase indeks kemiskinan di Tulungagung per Maret 2023 mencapai 6,53 persen. Menurut BPS, data itu sudah turun 0,18 persen ketimbang bulan Maret 2022 yang sebesar 6,71 persen.
Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung pada bulan Maret 2023 mencapai 68,81 ribu jiwa, mengalami penurunan 1,71 ribu jiwa terhadap bulan Maret 2022 yang sebesar 70,52 ribu jiwa.
Sedangkan garis kemiskinan di Kabupaten Tulungagung pada bulan Maret 2023 sebesar Rp.423.875,00 per kapita per bulan, atau meningkat sebesar 8,16 persen, ketimbang kondisi bulan Maret 2022 yang sebesar Rp 391.888,00.
Meski indeks kemiskinan di Tulungagung turun, dan garis kemiskinan naik apakah data itu tak cukup untuk menunjukkan bahwa 68,81 ribu jiwa penduduk miskin dan Rp.423.875,00 per kapita per bulan sebagai batas kemiskinan adalah realitas yang tak bisa diabaikan?
Otokritik
Menjamurnya gerai minimarket waralaba di desa-desa sebetulnya juga bisa dimaknai sebagai kritik agar pengelolaan toko kelontong tidak asal dan terkesan main-main.
Jika mau instropeksi, salah satu alasan kenapa minimarket itu tetap laris meski semua harga dagangannya relatif cukup mahal adalah karena pelayanan (service) dan manajemen yang prima.
Tegur sapa ramah kepada pelanggan ketika masuk, ruangan yang bersih, dagangan tertata rapi plus AC yang sejuk adalah salah satu alasan kenapa toko serba ada (toserba) itu tetap ramai meski terletak di desa-desa.
Bagi kelas menengah, wacana tentang higienisitas barangkali juga menjadi pertimbangan tersendiri. Anda mungkin pernah melihat bagaimana sebuah toko kelontong atau minimarket non-waralaba yang sebagian dagangannya ternyata kadaluwarsa.
Hal demikian menandakan bahwa toko tersebut boleh dibilang ceroboh karena bisa membahayakan kesehatan konsumen. Di sisi lain, mereka juga telah melakukan “bunuh diri ekonomi” karena pelanggannya kapok balik lagi.
Namun yang tak kalah menarik dari itu semua, masyarakat seolah tak merasa “terancam” dengan kehadiran minimarket waralaba di desa-desa mereka. Bahkan sebagian menyambutnya dengan suka cita.
Padahal kalau diamati dengan saksama, menjamurnya minimarket waralaba di desa-desa merupakan alarm bahaya bagi warung dan toko kecil (tentangga) kita. []