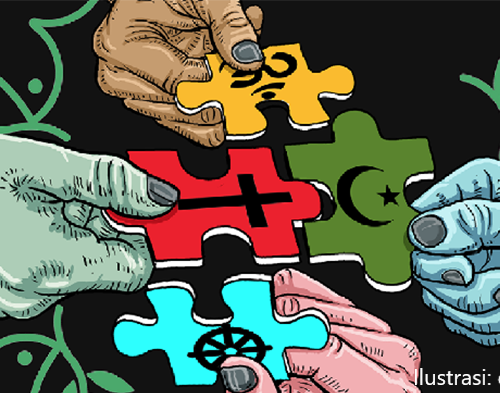Masyarakat Jawa terutama yang tinggal di daerah Mataraman—Madiun, Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Trenggalek dan Blitar—memiliki identitas diri sebagai masyarakat orang Jawa, antara lain: busana (pakaian), curiga (keris, pusaka Jawa kuno), wisma (rumah), turangga (kuda sebagai kendaraan), dan kukila (burung perkutut).
Itulah lima identitas masyarakat Jawa yang merupakan kekayaan warisan atau peninggalan leluhur Jawa yang adiluhung. Identitas budaya Jawa tersebut merupakan simbol dan terdapat makna falsafah yang mengandung nilai-nilai hidup religius-spiritual, di samping nilai etika dan estetikanya.
Saya sebagai orang kelahiran di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur merasa bangga dan senang terhadap identitas masyarakat Jawa yang ditandai dengan lima hal tersebut di atas.
Sebab, sebagai orang yang dibesarkan di daerah Tulungagung Jawa Timur, saya bersinggungan langsung dengan identitas masyarakat Jawa tersebut dalam kehidupan saya sampai sekarang ini.
Busana (Pakaian)
Busana alias pakaian khas masyarakat Jawa. Busana laki-laki disebut beskap dengan dilengkapi jarit (pakaian bawah) dan blangkon (penutup kepala) serta selop (sandal yang khas).Dalam acara-acara tertentu, para bapak yang mengenakan busana kejawen (khasanah budaya Jawa) tersebut ditambah lagi dengan mengenakan kerisatau curiga yang dikenakan di bagian belakang (punggung).
Sementara, busana para ibu atau kaum perempuan Jawa disebut kebayak dengan mengenakan jarit (di bagian bawah), mengenakan sandal yang khas pula, memakai selendang, serta rambutnya disanggul dengan memakai gelungan (konde).
Dengan mengenakan busana yang lengkap seperti itu, baik para bapak (laki-laki) maupun para ibu (perempuan), maka mereka terlihat dengan jelas telah menunjukkan identitas sebagai Jawa.
Dengan mengenakan busana tersebut, jelas mereka telah memberikan penghormatan kepada para leluhur orang Jawa yang telah mewariskan busana sebagai identitas budaya masyarakat Jawa yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di kancah internasional. Selain merupakan identitas orang Jawa, busana tersebut juga mencerminkan nuansa etika dan estetika (keindahan).
Curiga (Keris, Pusaka)
Curiga disebut pula dengan keris atau disebut pusaka sebagaimana yang dipakai sebagai senjata andalan orang Jawa zaman dulu. Secara umum, curiga atau keristersebut ada dua fungsi atau kegunaannya yakni keris ageman dan keris pusaka tayuhan.
Keris ageman yaitu keris yang biasanya dipakai dalam acara-acara tertentu dalam tradisi masyarakat Jawa seperti acara resepsi pernikahan, upacara adat, jamasan keris, dan sebagainya, sedang keris pusaka tayuhan identik dengan kerissebagai senjata atau secara umum disebut sebagai piyandel (kesaktian). Namun dalam konteks ini, keris ageman lebih berfungsi sebagai estetika atau keindahan yang dikenakan oleh masyarakat Jawa dalam acara-acara tertentu.
Sementara kerisatau pusaka pada zaman dahulu sering dipakai sebagai piyandel atau kesaktian oleh para raja dan satriya terutama para senapati serta prajurit. Biasanya keris (curiga) merupakan karya seorang empu yang ‘mempunyai kekuatan’ atau daya magis (Koesni, 1979).
Yang menarik lagi bahwa curiga atau kerisbagi masyarakat Jawa merupakan falsafah hidup yang sangat esensial. Dalam konteks ini, curiga atau keris merupakan simbol Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini sebagai lambang kekuatan gaib Ilahi.
Hal tersebut diungkapkan Seno Sastroamidjojo (1964) bahwa Tuhan bersifat Tunggal, sehingga oleh orang Jawa diilustrasikan dalam Ilmu Kejawen dengan curiga atau keris juga bersifat tunggal yang dimanifestasikan seperti huruf Alif (dalam Bahasa Arab) atau seperti angka 1 (monoteisme).
Angka 1 atau huruf Alif dalam Bahasa Arab dijadikan sebagai tingkat atau lajer yang bermakna ‘pokok’ atau ‘moyang’. Dan, angka 1 merupakan suatu permulaan deretan angka, begitu pula dengan Alif juga sebagai permulaan huruf Hija’iyyah.
Demikian pula, kata Seno, Tuhan—dalam kehidupan ini—sebagai permulaan atau pokok pangkal segala sesuatu di dalam dan di luar seluruh semesta alam. Atau kalau dalam Asmaul Husna, Allah adalah Dzat yang Maha Awal (permulaan).
Sementara itu, wadah atau tempat curiga atau kerisdisebut warangka, sehingga keberadaan warangka menyelubungi atau menutupi curiga atau keris. Dalam hal ini di dalam masyarakat Jawa ada falsafah warangka manjing curiga yang artinya manunggaling kawula lan Gusti atau identik pula dengan falsafah mati sajroning urip.
Selain itu, sebagaimana kita ketahui bahwa curiga atau kerismerupakan karya para empu atau leluhur orang Jawa yang memiliki estetika tinggi, sehingga ditetapkan sebagai ‘Karya Agung Budaya Dunia’ oleh UNESCO pada tanggal 25 November 2005.
Bagi masyarakat Jawa, curiga (keris) sebenarnya juga mencerminkan isyarat simbolis yang mendalam mengenai religius-spiritual, karena terkait dengan konsep Pantheisme dan Monoteisme.
Menurut Zoetmulder (1991), Pantheisme adalah paham yang mengatakan bahwa dunia terlebur dalam Tuhan; dengan kata lain bahwa dunia merupakan bagian dari hakikat-Nya.
Sedang Monisme adalah paham yang mengatakan bahwa Tuhan terlebur di dalam dunia, sehingga dunia merupakan ada yang tunggal dan mutlak. Pantheisme dan Monisme pada dasarnya berakar pada pendapat bahwa segala sesuatu bersifat Tunggal.
Dalam tradisi masyarakat Jawa yang telah mengakar diketahui bahwa istilah ‘warangka manjing curiga’ diilustrasikan ketika Bima manjing ke dalam Dewa Ruci (Pantheisme); sedangkan dalam cerita Bimapaksa atau Bimasuci mengesankan ‘curiga manjing warangka’ karena Dewa Ruci digambarkan manjing ke dalam tubuh Bima.
Demikianlah yang tersirat dari makna curiga (keris) bagi ‘manusia Jawa’ sebagaimana dijelaskan oleh Purwadi dalam Penghayatan Keagamaan Orang Jawa: Refleksi atas Religiusitas Serat Bima Suci. Hal ini berarti melekatnya konsep ‘Manunggaling kawula-Gusti’ atau disebut juga dengan ‘wihdatul wujud’, sehingga melahirkan istilah ‘curiga manjing warangka, warangka manjing curiga.’
Sementara, Simuh (1988)berargumen bahwa paham—terutama yang berkembang di masyarakat Jawa pedalaman—mengenai masuknya (nitis) roh Dewa ke dalam diri manusia atau roh manusia dalam binatang masih terungkap di dalam Wirid Hidayat Jati.
Sedangkan, roh manusia yang sesat tidak dapat kembali ke dalam singgasana Tuhan, karena akan nitis dan bergabung ke dalam alam brakasakan (jin jahat), bangsa burung, binatang dan air.
Wisma (Rumah)
Masyarakat Jawa terutama daerah Mataraman juga memiliki identitas yaitu wisma atau rumah yang sangat khas yang berbentuk limas; yakni bagian tengahnya menjulang tinggi ke atas. Secara umum, rumah model limas tersebut ada dua tipe, yaitu tipe Dwarawati (nama negara Prabu Sri Bathara Kresna) dan tipe Mandura (nama negara Prabu Baladewa).
Tipe Dwarawati atau Mandura ini dimaksudkan sebagai kharakterisasi tipe rumah sesuai dengan kondisi fisiknya. Artinya tipe Dwarawati ukurannya kecil, sedang tipe Mandura ukurannya lebih besar.
Bagi masyarakat Jawa pada zaman dulu yang hidup terpandang biasanya memiliki wisma atau rumah yang terdiri antara lain ada bale (balai besar yang fungsinya sebagai ruang tamu dan untuk nanggap wayang) dengan menghadap selatan.
Sedangkan di belakangnya ada rumah limas yang identik dengan rumah induk, sedang di sebelah timurnya ada rumah besar dan di belakangnya dapur untuk memasak.
Turangga (Kuda sebagai Kendaraan)
Turangga atau kuda adalah kendaraan atau tunggangan bagi orang-orang Jawa di zaman dulu. Secara filosofis, turangga sebenarnya melambangkan empat nafsu manusia; dilambangkan dengan empat kaki turangga.
Di pedesaan—terutama di Jawa pedalaman wilayah selatan—sangat marak atraksi permainan jaranan (kuda-lumping). Itulah isyarat mengenai kuda berkaki empat yang merupakan simbol dari empat nafsu manusia; yakni nafsu ammarah, lawwamah, supiyah (mulhimah), dan muthmainnah.
Penggambaran empat nafsu dalam diri manusia tersebut sinkron dengan simbol-simbol nafsu dalam pewayangan yaitu empat bersaudara, anak-anak Prabu Wisrawa (Raja Alengkadiraja). Yakni nafsu ammarah identik dengan gambaran Prabu Dasamuka alias Rahwana Raja, seorang raja Alengkadiraja yang jahat. Nafsu lawwamah atau aluamah disimbolkan Kumbakarna yang suka tidur dan makan.
Sedangkan, nafsu mulhimah atau supiyah dilambangkan Dewi Sarpakenaka yang gampang tergoda asmara kepada Raden Laksmana. Dan yang nafsu muthmainnah digambarkan sifat dan watak Raden Wibisana yang kemudian bergabung dengan titising Bathara Wisnu yaitu Sri Rama Wijaya, sehingga bermusuhan dengan kakaknya sendiri Prabu Dasamuka.
Kukila (Burung Perkutut)
Kukila yaitu burung, tetapi dalam hal ini biasanya identik dengan burung perkutut atau biasanya disebut oleh orang Jawa manuk kutut. Sejak zaman dulu, orang Jawa memiliki kebiasaan memelihara burung perkutut atau manuk kutut yang biasanya dimasukkan di dalam sangkar dan dipajang depan rumahnya.
Dalam hal ini ada unsur estetika atau keindahan dari suara burung perkutut yang biasanya disebut kung (untuk menyebut merdu suara burung perkutut) atau disebut bagus anggung-nya. Itulah sebabnya, mahalnya harga burung perkutut tersebut dilihat dari kung-nya suara burung perkutut itu sendiri.
Burung di dalam sangkar, sebenarnya merupakan metafora atau perumpamaan antara hati (nurani) dengan badan wadhag (fisik; jasmaniah) atau antara yang bersifat batiniah dan lahiriah.
Dalam Kejawen juga terdapat wacana mengenai ‘burung’ ibarat suksma dalam diri manusia, sedang sangkar burungnya melambangkan badan wadhag atau fisik manusia. Dalam Tembang Macapat (Dhandhanggula), misalnya, tersirat mengenai ilustrasi ‘burung’ dengan sangkarnya:
“Dipun weruh ing urip sejati// Lir kurungan reraga sadaya// Becik den wruhi manuke// Rusak yen sira tan wruh// Heh Ra Wujil salaku neki// Iku mangsa dadia// Yen sira yun weruh// Becikana kang sarira// Awismaa ing enggon ponang asepi// Sampun kacakrabawa.”
Tembang Macapat (Dhandhanggula) tersebut merupakan wejangan (nasihat) Sunan Bonang kepada Rara Wujil, muridnya yang sedang berguru ‘ngelmu kasampurnan’.
Seseorang yang menginginkan hidup yang sejati, sebagaimana yang dijelaskan Sunan Bonang kepada Rara Wujil, hendaknya ia berusaha melihat ‘burung’-nya sendiri di dalam sangkar kewadhagan-nya; “becik den wruhi manuke.”
Adapun caranya, Sunan Bonang memerintahkan kepada Rara Wujil agar ia bertempat tinggal di tempat yang sepi atau sunyi, yakni diungkapkan dalam tembang; “Yen sira yun weruh, becikana kang sarira, awismaa ing enggon ponang asepi.” []