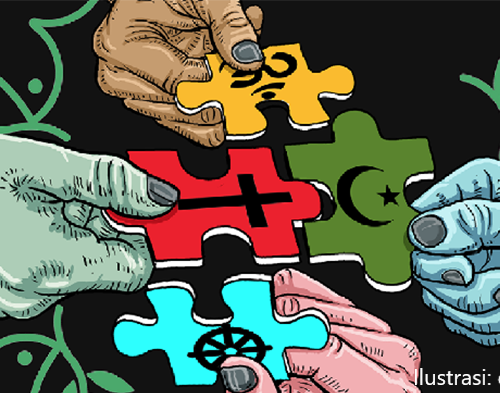Demokratisasi pengetahuan melalui perkembangan teknologi informasi memang seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, ia memudahkan namun di sisi lain juga mengkhawatirkan. Taruhlah urusan pengetahuan tentang ilmu agama sebagai contohnya. Dulu, sebelum media sosial ramai seperti sekarang, belajar agama hanya bisa dilakukan melalui buku atau kitab yang dipimpin oleh ustaz atau kiai. Sekarang tidak lagi. Kita bisa sangat mudah mengakses ceramah-ceramah agama via media sosial seperti Youtube, Facebook maupun Instagram.
Celakanya, keterbukaan arus informasi itu, ternyata juga memberikan andil terhadap merebaknya pemahaman kaku dan sempit perihal ke(be)ragam(a)an. Baru-baru ini kita disuguhi oleh video amatir seorang laki-laki yang mengalami perundungan dan kekerasan akibat memakai masker di dalam masjid. Video itu terjadi di Masjid Al Amanah, Kelurahan Pejuang Jaya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 27 April 2021 yang lalu.
Dalam video yang berdurasi kurang lebih 02 menit 02 detik itu tampak seorang laki-laki bermasker sedang duduk dan dikerumuni oleh tiga orang laki-laki yang sedang meledakan amarah sembari menuding-nuding jamaah tersebut. Usut punya usut, tiga orang itu tidak terima karena ada jamaah yang salat dengan memakai masker karena menurutnya masjid tidak sama dengan pasar. Si korban kekeuh dengan anjuran pemerintah agar tetap memakai masker sebagai protokol kesehatan. Sedangkan pengurus masjid juga tak kalah ngotot dengan aturannya dan bersandar pada potongan QS. Ali Imran ayat 97 (awalnya yang disebutkan bukan ayat 97 melainkan ayat 96) bahwa “Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia.” Bahkan salah satu dari pengurus masjid—anak muda berbaju merah itu—tega menyeret jamaah keluar masjid.
Kalu kita mau sedikit berpikir, sedikit saja, bukan berarti orang yang pakai masker itu tidak percaya dengan ayat al-Qur’an dan lebih memilih percaya pada anjuran pemerintah. Namun semua orang di dunia juga tahu, kalau sekarang masih pandemi. Bahkan di Masjidil Haram, tanah suci itu, semua jamaah juga diwajibkan untuk memakai masker dan menjaga protokol kesehatan. Apakah itu berarti pemerintah Arab tidak percaya nash Tuhan? Tentu saja tidak. Namun ada kaidah ushul fikih yang menyatakan bahwa mencegah atau menghindari kerusakan (dar’ul mafasid) lebih utama daripada kemaslahatan. Kecuali bagi mereka yang sampai saat masih meyakini bahwa virus Covid-19 hanyalah konspirasi.
Nah, peristiwa itu cukup memberi gambaran pada kita betapa nalar itu penting dalam beragama. Tanpa nalar—meminjam istilahnya Arkoun—teks-teks keagamaan akan berhenti pada monopoli kebenaran tunggal (single truth) yang tampak rigid, stagnan, menyeramkan dan kehilangan konteksnya sesuai dinamika sosial yang ada. Sebab ada jarak menganga antara teks dengan realitas dan modernitas. Bahkan bisa menjadi semacam “berhala wacana” dan “logosentrisme” yang seolah justru menenggelamkan aspek fundamental dari Islam, yaitu ra(h)mah.
Politik Identitas & Habitus Rigiditas
Salah satu penyebab kenapa habitus rigid dan takfiri semakin meningkat lantaran iklim politik identitas yang tidak selesai. Meski momen Pilgub dan Pilpres sudah lama berlalu, namun percik api kebencian masih terjaga atau bahkan meningkat. Term “kampret,” “cebong” dan “kadrun” masih sangat mudah kita temukan berseliweran di kolom komentar berbagai lini media sosial. Padahal momen pemilu sudah lama berlalu dan dua kubu yang (tampak) berseteru juga sudah menjadi satu.
Kalau menilik dari sudut pandang Bourdieu dalam (Najib Yuliantoro, 2016), maka habitus rigid sesungguhnya merupakan situasi yang mencerminkan kondisi sosial tempat individu tersebut berada. Itu semua dipengaruhi dan diperoleh melalui proses pembiasaan, pengalaman, penularan atau pembelajaran yang berulang-ulang baik sadar maupun tidak. Habitus mengandung unsur “pasivitas”; menerima keniscayaan sampai tak disadari sehingga tak sempat didiskusikan. Habitus juga mengandung unsur “ilusio”; mengandaikan sesuatu yang sebenarnya tak ada.
Tanpa nalar—meminjam istilahnya Arkoun—teks-teks keagamaan akan berhenti pada monopoli kebenaran tunggal (single truth) yang tampak rigid, stagnan, menyeramkan dan kehilangan konteksnya sesuai dinamika sosial yang ada. Sebab ada jarak menganga antara teks dengan realitas dan modernitas.
Dengan demikian saya menduga bahwa anak muda berbaju merah dan takmir bergamis—yang sikapnya keras minta ampun itu—adalah reperesentasi lingkungan yang ia geluti. Hal itu bisa dibentuk oleh apa yang ia baca, dengar dan yakini selama ini. Meski saya juga yakin, di era digitalisasi seperti sekarang ini, anak-anak muda yang sedang bergairah belajar agama bisa dengan mudah mengakses pengetahuan melalui video-video yang tersebar di Youtube dan media sosial lainnya. Akibatnya, arogansi dalam beragama seringkali menjadikannya buta dan lupa bahwa Islam mengajarkan kesantunan, keramahan dan tentu saja kemanusiaan kepada semua umat manusia dari berbagai latar belakang agama.
Dalam hal menjalin hubungan antarmanusia, baik secara individu dan masyarakat, al-Qur’an juga tegas menawarkan etika hubungan yang humanis, karena al-Qur’an yang dibawa Nabi Muhammad itu hadir untuk membawa rahmat bagi seluruh alam (al-Anbiya’: 107). Karena itu ia mendorong umat manusia untuk saling mengenal (al-Hujarat:13), mengajak pada kebaikan dan melarang perbuatan munkar (Ali Imran: 104), mengajurkan tolong-menolong (al-Maidah: 2), bersikap adil dalam berhubungan dengan pihak lain (al-Maidah: 8). Al-Qur’an melarang permusuhan, berbuat jahat, teror dan konflik apalagi berperang dan saling membunuh (al-Anam: 15) (Aksin Wijaya, 2019).
Sehingga dalam kasus “privatisasi” tempat ibadah tadi, harus dipahami bahwa masjid sebagai tempat ibadah umat Muslim adalah ruang publik. Sebagai tempat peribadatan publik maka masjid seharusnya bebas dari intimidasi dan dominasi ideologi. Meskipun lazim diketahui bahwa secara kultural-struktural banyak masjid yang dekat dengan organisasi masyarakat seperti NU maupun Muhammadiyah. Hanya saja dua Ormas itu tidak pernah menghilangkan karakter publik masjid sebagai tempat ibadah bagi semua umat Islam.
Terakhir, sebagai counter wacana dan upaya untuk ikut bersumbangsih menyebarluaskan Islam yang ramah (smiling of Islam) di kalangan anak muda, maka dibutuhkan pribumisasi konten dakwah di dunia maya. Pemerintah harus bekerjasama dengan Ormas yang berhaluan moderat untuk terus-menerus memproduksi dan mempromosikan secara massif konten dakwah ramah di berbagai platform media sosial. Hal ini dimaksudkan agar wacana tentang Islam eksklusif tidak menduduki urutan pertama dalam mesin pencarian Google maupun platform media sosial lainnya. Dan jangan lupa, gunakanlah akal juga dalam beragama agar tidak taklid buta dan kelihatan tak pernah dididik oleh orang tua. []