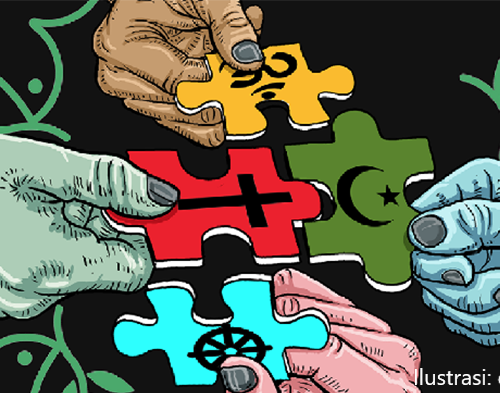Kebudayaan Jawa memiliki kekayaan tradisi yang kompleks dan mendalam. Di sisi lain, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia juga membawa berbagai pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Salah satu tradisi yang mencerminkan integrasi antara kebudayaan Jawa dan Islam adalah tradisi Suroan.
Tradisi ini, yang bertepatan dengan bulan Muharram dalam kalender Islam, menggabungkan elemen-elemen budaya Jawa dengan nilai-nilai Islam. Esai ini akan mengkaji bagaimana integrasi ini terjadi, fenomena sosial yang menyertainya, serta analisis filosofis berdasarkan pemikiran dan teori-teori dari para tokoh.
Tradisi Suroan, yang juga dikenal sebagai Grebeg Suro di beberapa daerah, merupakan perayaan yang diadakan pada bulan pertama dalam kalender Jawa dan Islam, yaitu bulan Suro atau Muharram.
Tradisi ini memiliki akar yang kuat dalam kebudayaan Jawa sebelum Islam masuk ke Nusantara. Bulan Suro dianggap sebagai bulan yang sakral sebab banyak ritual dilakukan untuk menjaga keseimbangan alam dan mendekatkan diri kepada Tuhan.
Baca juga esai lain dari Gilang Tahes: https://diskursusinstitute.org/2021/06/11/ki-ageng-suryomentaram-filsuf-jawa-penggagas-kawruh-jiwa/
Dengan masuknya Islam ke Jawa, tradisi Suroan mengalami perubahan dan integrasi. Nilai-nilai Islam yang menekankan monoteisme, keadilan, dan kemanusiaan diintegrasikan ke dalam ritual dan perayaan bernuansa kearifan lokal.
Contoh nyata dari integrasi ini adalah ritual tirakatan Suro. Pada momen ini, masyarakat mengadakan doa bersama dan pengajian sebagai bentuk syukur dan mawas diri.
Selain itu, di masyarakat pesisir pantai selatan Jawa ada sebuah tradisi Suro yang telah lama dilestarikan: Larung Sesaji. Larung Sesaji adalah ritual membuang sajen ke laut sebagai tanda syukur dan permohonan perlindungan dari bencana kepada Allah Swt.
Meskipun asal-usul ritual ini adalah animisme dan dinamisme, elemen-elemen Islam seperti doa-doa dan zikir sering kali disertakan dalam pelaksanaannya. Fenomena ini menunjukkan bagaimana masyarakat Jawa mampu menggabungkan tradisi lokal dengan ajaran Islam secara harmonis.
Dalam padangan Clifford Geertz dalam The Religion of Java (1960), sinkretisme ini adalah salah satu ciri khas kebudayaan Jawa yang sangat adaptif dan fleksibel. Geertz menyebutnya sebagai “Agami Jawi” atau agama Jawa, yang merupakan perpaduan antara kepercayaan Hindu-Budha, Islam, dan animisme lokal.
Meskipun belakangan, banyak sarjana Barat lain yang mengkritik tesis Geertz tentang “sinkretisme” dan “Agama Jawa” tersebut. Sebab Islam di Jawa tidaklah sinkretik melainkan asimilatif.
Hal demikian misalnya bisa kita lihat pada kritik Robert W. Hefner dalam Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam (1985) kepada Geertz yang dianggap terlalu menekankan aspek simbolis dan budaya tanpa mempertimbangkan dinamika kekuasaan dan politik yang mempengaruhi proses sinkretisme. Pun belakangan tesis Hefner ini juga keliru sebab masyarakat Tengger sesungguhnya bukanlah Hindu.
Talal Asad juga pernah menguliti pandangan Geertz tentang konsep sinkretisme. Dalam Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam (1993), ia memperkenalkan pendekatan genealogis untuk memahami agama.
Agama menurut Asad tidak bisa dipahami hanya sebagai sistem simbol, tetapi juga harus dilihat sebagai praktik yang terkait erat dengan struktur kekuasaan dan kontrol sosial. Ia menekankan pentingnya memahami bagaimana institusi agama berfungsi dalam konteks politik dan sosial.
“Meskipun belakangan, banyak sarjana Barat lain yang mengkritik tesis Geertz tentang “sinkretisme” dan “Agama Jawa” tersebut. Sebab Islam di Jawa tidaklah sinkretik melainkan asimilatif.”
Sedangkan yang dimaksud “Agama Jawa” oleh Geertz adalah Islam dalam berbagai corak dan manifestasi ke(be)ragama(a)nnya. Padahal “Agama Jawa” itu sendiri sesungguhnya bukanlah Islam seperti yang dimaksud olehnya. “Agama Jawa” yang sesungguhnya lebih menekankan kepada kepercayaan dan kebatinan yang lahir dari bumi Nusantara.
Di sisi lain, fenomena integrasi budaya Islam dan Jawa juga sebenarnya mirip dengan apa yang disinggung oleh Homi K. Bhabha—salah satu tokoh ahli pascakolonial—sebagai konsep hibriditas.
Dalam bukunya The Location of Culture (1994), ia menyebutkan bahwa konsep hibriditas adalah suatu penciptaan ruang budaya baru di mana identitas ganda atau lebih dapat berdialog dan berinteraksi.
Maka tradisi Suroan bisa dilihat sebagai bentuk hibriditas; suatu fenomena ketika identitas budaya Jawa dan Islam tidak saling menegasi, tetapi saling melengkapi.
Pada perspektif lain, Anthony Giddens dalam bukunya, The Consequences of Modernity (1990) juga mengemukakan bahwa tradisi dan modernitas tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, tetapi bisa saling melengkapi dalam membentuk identitas sosial.
Tradisi Suroan menunjukkan bagaimana masyarakat Jawa mampu mempertahankan kearifan lokal mereka sambil mengadopsi nilai-nilai Islam, menciptakan identitas yang dinamis dan adaptif di era modern.
Contoh lain dalam konteks ini bisa dilihat pada perayaan Grebeg Maulud di Yogyakarta. Festival dan ritual dalam Grebeg Maulud merupakan cerminan integrasi budaya Jawa dan Acara ini juga menggabungkan elemen-elemen tradisional Jawa seperti iring-iringan prajurit keraton, gunungan (tumpeng besar berbentuk gunung), dan doa-doa islami.
Hal demikian selaras dengan pendapat Suwardi Endraswara (2006), bahwa tradisi tersebut adalah contoh nyata bagaimana masyarakat Jawa mampu menggabungkan elemen-elemen Islam dengan tradisi lokal untuk menciptakan identitas budaya yang unik dan kohesif.
Dengan demikian, berbagai padangan tokoh di atas menjadi menarik untuk dijadikan sebagai pijakan dalam memandang tradisi Suroan sebagai ekspresi integrasi budaya Jawa dan Islam.
Hibriditas menunjukkan bahwa identitas budaya tidak statis, tetapi selalu dalam proses menjadi, dengan memadukan elemen-elemen yang berbeda untuk menciptakan sesuatu yang baru.
Sementara itu, konsep tradisi dan modernitas Giddens membantu kita memahami bagaimana masyarakat Jawa mampu mempertahankan tradisi lokal mereka sambil mengadopsi nilai-nilai Islam dalam konteks yang lebih luas.
Pada akhirnya kita dapat memahami bahwa integrasi kebudayaan Jawa dan Islam dalam tradisi Suroan adalah contoh nyata dari bagaimana masyarakat mampu merawat ke(be)ragama(a)n tanpa harus tercerabut dari akar tradisi dan budayanya. Dalam konteks inilah, tradisi Suroan dapat menjadi inspirasi untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan toleran. []