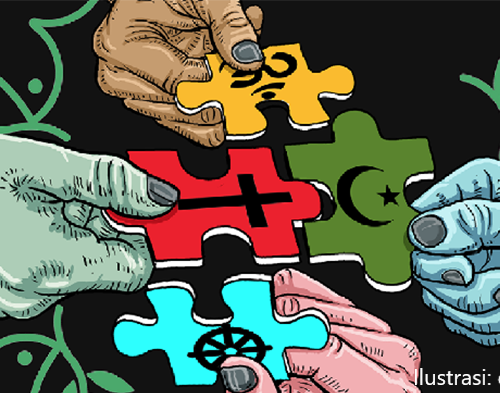Esai ringan ini sesungguhnya merupakan sempalan kecil dari riset saya tentang perjalanan panjang salah satu suku di selatan pulau Borneo. Ya, orang menyebutnya dengan suku Banjar.
Dalam perjalanan sejarah, suku Banjar pada akhirnya mengalami apa yang disebut oleh beberapa peneliti sebagai ‘diaspora.’ Dalam konteks ini, saya menemukan dua latar belakang diaspora tersebut.
Pertama, pola diaspora suku Banjar ke Pulau Jawa menolak teori leaping frog-nya Edi Susrianto yang membaca kecenderungan suku Banjar bermigrasi tidak langsung menuju lokasi final, melainkan menyinggahi terlebih dahulu wilayah-wilayah yang mereka lewati.
Pola ini lazim terjadi di Sumatra dan Malaysia sebagai lokasi final yang mereka hendak tuju. Namun pada faktanya, kehadiran suku Banjar ke Tulungagung justru menggunakan pola langsung (direct mobility).
Kedua, saya juga menolak teori Potter—seorang sarjana Inggris—yang menjelaskan bahwa migrasi suku Banjar akan memilih tempat seperti pelabuhan dan rawa untuk didiami. Pelabuhan merupakan habitat dari lahirnya suku ini di pesisir selatan Kalimantan.
Sedangkan rawa adalah pilihan bagi mereka yang memilih menjadi petani dan pekebun ketimbang harus menjadi pedagang dan nelayan seperti jamaknya profesi suku Banjar di pertengahan abad ke 16.
Nyatanya di Jawa, baik di Yogyakarta, Solo, Surabaya, maupun Semarang, profesi berbisnis emas lebih mereka geluti ketimbang temuan konklusi yang disuguhkan oleh Potter tersebut.
Nah, dalam konteks inilah maka esai ini akan mengulas lebih dalam lagi tentang ‘mengapa’ dan ‘bagaimana’ suku Banjar bermigrasi, khususnya di Bumi Gayatri Tulungagung.
Kampungdalem sebagai Tempat Tujuan
Jika Anda kebetulan bertemu atau kenal dengan orang keturunan suku Banjar yang bertempat tinggal di Tulungagung maka predikat dan identitas yang melekat adalah mereka sebagai pebisnis emas sukses.
Citra demikian memang tak salah. Sebab dalam catatan Singgih Tri Sulistiyanto (2011) misalnya, bahwa keberadaan etnis Banjar di Tulungagung sudah ada sejak awal tahun 1920-an.
Di Tulungagung, etnis ini identik dengan bisnis emasnya yang terbilang sukses. Selain mahir dalam berdagang, etnis Banjar juga dikenal sangat agamais dan memiliki jiwa korsa yang tinggi.
Hingga saat ini, warga keturunan Banjar yang mendiami di daerah Kampungdalem Tulungagung adalah generasi ke 5 sejak generasi awal hijrah pada awal tahun 1900-an.
Lebih lanjut, Subekti (2009) menuturkan bahwa jumlah etnis Banjar yang memilih eksodus ke Tulungagung jumlahnya lebih besar ketimbang etnis Tionghoa dan Arab.
Dalam sejarahnya, mereka pertamakali menetap di Kampungdalem—sebuah distrik yang dekat sekali dengan jantung kota dan pusat pemerintahan Tulungagung.
“Semua nilai, sikap dan pandangan-pandangan warga keturuan Banjar di Tulungagung telah menumbuhkan sebuah “ekosistem” ekonomi yang memegang teguh etika dalam berbisnis.”
Secara kronologis, suku Banjar mengikuti peta dagang warga Tionghoa dari Tuban, dan Surabaya yang memilih menyusuri sungai Brantas untuk menjelajahi pedalaman selatan Jawa.
Pada periode awal tahun 1960-an, warga Banjar dan Jawa mengalami asimilisasi budaya lewat jalur perkawinan. Sehingga generasi yang ada saat ini adalah generasi campuran atau hibrid, bukan lagi etnis asli Banjar.
Selain tinjauan itu, peta sosial masyarakat Jawa yang cenderung legawa dan adaptif, memperlihatkan suatu watak pertemuan yang harmonis antara keduanya.
Spirit Kapitalisme dan Etos Kerja
Mula-mula permata adalah komoditas barang dagangan yang dijajakan oleh suku Banjar di awal tahun 1920-an. Hj. Ruman adalah saudagar perempuan permata kaya raya yang datang langsung dari Desa Pagar Alam di Kalimantan Selatan sana (Subekti, 2009). Namun lantaran permata dirasa terlalu mahal dan kurang diminati oleh pasar, mereka pada akhirnya beralih berjualan emas hingga saat ini.
Sebagai suku yang gemar bermigrasi, menjadi pedagang adalah pola adaptasi yang sering berhasil mengantarkan mereka sukses di wilayah baru yang mereka diami. Ini mirip seperti suku Madura yang juga gemar bermigrasi ke sana-sini.
Robert Young dalam “The English Factory at Banjar on the Island of Borneo,1699–1707,” mencatat bahwa, sejarah Banjarmasin pada abad ke 16 dan 17 telah dikenal sebagai kota perdagangan rempah, khususnya lada.
Sebagai kota modern pada eranya, Banjarmasin pada masa itu telah menghasilkan aturan-aturan hukum yang berfungsi sebagai pengawas dan pengendali kegiatan perdagangan dan kemasyarakatan. Bahkan, Banjarmasin yang masyarakatnya multi-warga tersebut menumpukan kekuatan ekonominya kepada perdagangan dan pelayaran.
Dari hasil penelusuran saya, meski banyak warga keturunan Banjar yang sukses dengan berdagang emas akan tetapi hal itu bukan berarti mereka tidak menjual barang lainnya. Ada juga warga keturunan Banjar yang berdagang selain emas, seperti penyedia fashion (konveksi dan distributor pakaian), logistik rumah tangga (sembako, meubeler) dan lain sebagainya.
Ada tiga temuan menarik dalam variable dinamika bisnis yang mereka geluti. Pertama, soal sedekah. Sebagai pedagang sukses, warga keturunan Banjar memegang teguh prinisp bersedekah dalam setiap profitnya.
Mereka berkeyakinan bahwa bersedekah sebagai tameng pelindung dari ancaman bahaya. Hal tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa dengan bersedekah maka harapannya adalah dijauhkan dari kerugian saat berdagang sekaligus dilipatgandakan keuntungannya.
Kedua, politik bisnis. Hal ini dimulai dari perekrutan karyawan. Para pebisnis Banjar akan memprioritaskan sanak famili (masih keturunan sesama Banjar) untuk ikut terlibat membantu menjalankan bisnisnya.
Masih dalam variable yang sama, pedagang Banjar tidak memandang pesaing bisnisnya adalah kompetitor yang harus disingkirkan. Mereka menanamkan pada diri mereka bahwa pesaing itu bukan perebut keuntungan.
Karena bagi warga keturunan Banjar, keuntungan adalah bentuk rezeki yang sudah diatur oleh Allah. Jadi tidak ada pesaing yang perlu dikahwatirkan karena Allah sudah mengatur rezeki hamba-Nya.
Ketiga, adalah konsep keseimbangan. Konsep baibadah dan bausaha telah mendinamiskan praktik-praktik ekonomi pedagang Banjar. Gagasan tentang keseimbangan antara baibadah dan bausaha menunjukkan bagaimana seriusnya etnis Banjar dalam memadukan unsur duniawi dan ukhrawi. Pedagang Banjar menjadi memiliki watak tekun, kerja keras serta tidak gampang putus asa.
Hal ini mengingatkan saya pada tesis menarik Max Weber terkait etos kerja dan visi religiusitas. Meski dalam praktik ekonomi suku Banjar menunjukkan watak dasar dari kapitalisme, akan tetapi mereka tetap menyelaraskan dengan spritualitas.
Semua nilai, sikap dan pandangan-pandangan warga keturuan Banjar di Tulungagung tersebut telah menumbuhkan sebuah “ekosistem” ekonomi yang memegang teguh etika dalam berbisnis.
Sebuah sikap yang tidak mau terjebak pada arus kapitalisme liberal yang saling “mengisap” satu sama lain tanpa peduli sanak saudara, famili maupun etnisitas. []