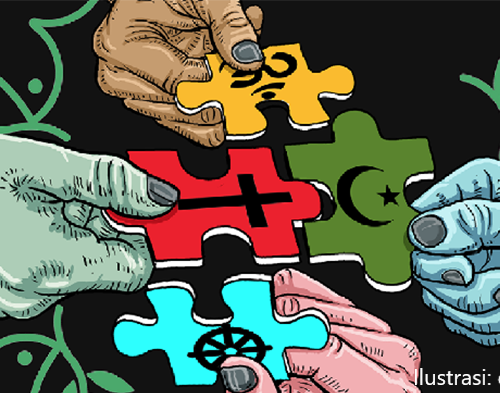Saya mungkin satu dari sekian orang yang boleh dibilang beruntung. Keberuntungan yang saya maksud adalah bisa mengenal dan masih menekuni dunia menulis hingga saat ini. Apalagi profesi saya sehari-hari juga lekat sekali dengan dunia tulis-menulis. Jadi semacam terbentuk sebuah habitus yang mendorong saya untuk tetap berada di “jalur” ini.
Saya kadang membayangkan, seandainya dulu Tuhan tidak mengantarkan saya kepada orang-orang hebat yang mengajari dan menginspirasi saya untuk menulis, bisa saja alur hidup saya berbeda dengan sekarang. Saya benar-benar mendapatkan banyak berkah dari dunia yang (mungkin) bagi beberapa orang dianggap suram ini.
Bagaimana tidak, profesi sebagai penulis itu—terlebih di Indonesia—sama sekali bukan pilihan menarik bagi mayoritas anak muda. Dalam pengamatan saya, ada dua sebab. Pertama, menjadi penulis itu bukan perkara gampang. Butuh penempaan diri yang tidak main-main. Meskipun Anda maniak baca (buku) misalnya, tak lantas menjadikan penulis secara bim salabim.
Sebab membaca dan menulis itu dua keterampilan yang berbeda. Tidak semua orang yang doyan baca itu bisa menulis. Tapi mereka yang suka menulis hampir bisa dipastikan suka membaca. Sebab tanpa membaca apa yang mau ditulis?
Kedua, menjadi penulis tak jelas masa depannya. Saya tak tahu darimana asumsi ini bermula dan seperti apa parameternya. Mungkin mereka melihat bahwa tak ada sama sekali yang membuka lowongan kerja sebagai penulis.
Ya, asumsi itu sesungguhnya tak salah tapi juga tak sepenuhnya benar. Sebab profesi penulis di Indonesia itu tak begitu mendapat apresiasi yang bagus. Maka tak aneh bila sangat sedikit sekali orang yang berani mengandalkan hidup hanya dengan menulis buku atau esai misalnya. Ya, hanya segelintir orang tangguh saja yang berani.
Namun bukan berarti bahwa memiliki skill menulis itu adalah tak berguna. Sebab kata Rhenald Khasali keterampilan menulis itu tak lantas membuat orang menjadi penulis. Ia bisa menjadi apa saja dengan logika berpikir yang teratur karena terbiasa menulis. Karena dengan menulis, seseorang akan berpikir kritis dan me-manage pikirannya secara kreatif.
Dengan kata lain, menulis itu tak lantas hanya menjadikan orang sebagai penulis saja. Ia bisa menjadi apa saja dengan logika berpikir yang tertata.
Penulis, Jurnalis, dan Sekretaris
Penulis itu beda dengan jurnalis. Penulis juga tak sama dengan sekretaris. Pun tugasnya sama-sama menulis. Ini berlaku juga bagi kalangan akademisi. Bukan berarti semua akademisi itu bisa menulis.
Kalau sekadar menulis artikel jurnal ilmiah untuk kredit poin atau kepangkatan sih barangkali bisa. Tapi belum tentu mereka bisa menulis dalam arti sesungguhnya.
Menulis kolom di media nasional macam Kompas, Tempo atau Tirto.id misalnya. Itu bukan perkara yang gampang. Kalau tak percaya silakan Anda coba.
“Sekolah mengajarimu membaca dan menulis tapi tak pernah memberi saran buku apa saja yang patut kau baca agar kau bisa menulis dengan baik.”
Penulis, jurnalis, dan sekretaris itu tugasnya memang sama-sama menulis. Tapi apakah makna penulis itu hanya bertugas untuk menulis? Lantas apa yang membedakan dari ketiganya? Jurnalis itu tugasnya adalah menulis berita.
Sedangkan sekretaris hanya bertugas mencatat, merekap atau menulis sesuatu yang diperintahkan oleh atasannya. Kalau penulis itu lebih dari itu. Meskipun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan “penulis” sebagai “pengarang” atau “orang yang menulis,” tapi nyatanya hakikat penulis tak hanya sebatas itu.
Kalau Anda buka Thesaurus dan memasukan kata kunci “author”, akan muncul lema sinonim seperti: kolumnis, kreator, jurnalis maupun reporter. Ini lebih sedikit komprehensif ketimbang KBBI.
Jadi definisi penulis itu secara terminologi lebih tepat disebut sebagai seorang yang menulis naskah entah itu fiksi maupun non-fiksi dan penuh konsistensi.
Kenapa ada kata konsistensi? Apakah yang tidak konsisten menulis misalnya, lantas tak layak disebut sebagai penulis? Mereka tetap dianggap sebagai penulis; penulis berkala alias kala-kala menulis kala-kala tidak.
“Suluk” Kepenulisan
“Suluk” dalam khazanah tasawuf diartikan sebagai “jalan sunyi”; jalan khusus dalam rangka menjalin keintiman dengan Sang Illahi. Nama orang yang melakukannya disebut sebagai salik.
Dalam konteks dunia kepenulisan, orang yang menempa diri dengan “berdarah-darah” untuk mencapai makamat sebagai penulis juga bisa disebut sedang “suluk”; lebih tepatnya “suluk” kepenulisan.
Tidak ada jalan pintas untuk menjadi seorang penulis. Sesering apa pun Anda mengikuti workshop kepenulisan yang digelar oleh penulis kawakan misalnya, juga tak lantas menjamin Anda menjadi penulis. Kecuali jika setelah itu, Anda benar-benar mempraktikkan berbagai teori itu secara sungguh-sungguh dan istikamah.
Sebab menulis itu learning by doing. Seseorang yang memutuskan untuk menjadi salik harus mengamalkan berbagai laku spiritual dari guru atau mursyid-nya. Itulah sebabnya, suluk diartikan sebagai jalan khusus yang tak semua orang mau dan mampu melakoni.
Menulispun juga demikian. “Suluk” kepenulisan hanya bisa dilalui dengan laku bukan teori. Laku yang harus ditempuh bagi seseorang yang sedang “suluk” kepenulisan juga bukan main-main. Ia harus merangsang kepekaannya terhadap realitas dan membaca sebanyak mungkin.
Kata Benedict Anderson (2016), “Orang harus punya rasa ingin tahu yang tak ada habisnya tentang segala sesuatu. Mempertajam telinga dan mencatat apa saja.”
Oleh sebab itu, menulis adalah perkara keteladanan. Itu tak bisa dilakukan hanya dengan motivasi apalagi instruksi. Sehingga kalau ada guru atau dosen yang menyuruh murid atau mahasiswanya menulis dengan menggebu-gebu sedangkan ia sendiri tak pernah melakukannya, itu sama dengan orang bermuka dua.
Kata A.S Laksana, “Sekolah mengajarimu membaca dan menulis tapi tak pernah memberi saran buku apa saja yang patut kau baca agar kau bisa menulis dengan baik.”
Baca juga: https://diskursusinstitute.org/2021/10/21/santri-transformasi-belajar-dan-tantangan-digital/
Ya, teladan adalah kunci penting di tengah arus krisis multidimensi seperti sekarang ini. Segala nilai-nilai kebaikan hanya bisa diwariskan melalui keteladanan. Begitu juga dengan menulis. Lagipula sekarang sudah banyak media online alternatif yang bisa dijadikan sebagai wahana untuk mengasah skill menulis kita. Ada yang memberikan sejumlah fee bagi penulisnya, dan ada juga yang tidak.
Namun poin pentingnya bukan itu. Jauh yang lebih penting dari sekadar fee menulis adalah proses menjadi; proses menjadi intelektual dalam arti sesungguhnya. Sebab menulis itu tak mengenal akhir, semakin sering kita menulis akan muncul berbagai pengalaman baru.
Dan semua itu harus dilalui dengan proses yang tak mudah. Seperti kata Nietzche, “Kau harus membakar diri dalam apimu sendiri; bagaimana mungkin kau bisa menjadi (manusia) baru jika tak menjadi abu terlebih dahulu.” []