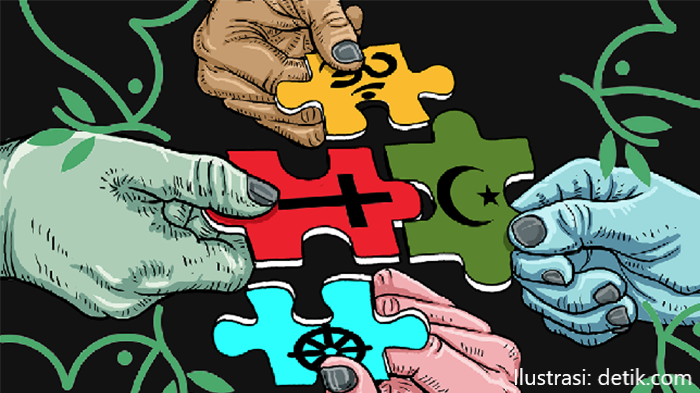Kita masygul menyaksikan kehidupan keagamaan yang rapuh. Hampir semua orang berapi-api memfestivalkan toleransi. Di saat yang sama, mereka juga menginjak-injaknya.
Baru saja Indonesia dibuat bangga oleh penandatangan Deklarasi Istiqlal (5/9/2024). Deklrasi itu diteken secara istimewa oleh Paus Fransiskus bersama Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Nasaruddin Umar. Suatu proklamasi bahwa Indonesia bangsa toleran.
Namun belum genap satu bulan, kita semua sudah “meludahi” deklarasi itu. Sekumpulan orang mengatasnamakan agamanya yang suci, beramai-ramai menolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel, di Parepare, Sulawesi Selatan (20/9/2024).
Konon, aksi ini didukung juga oleh politisi dan oknum pemerintah. Di banyak aksi kebencian seperti ini, rakyat jelata sering berbagi peran dengan penguasa, bahu-membahu menistakan kelompok yang dianggap beda.
Masih di bulan yang sama, warga Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Setempat (PGIS) Bekasi, juga diusir oleh gerombolan orang yang tidak ingin wilayahnya “ternodai” oleh kegiatan ibadah agama lain.
Sekali lagi, alasannya—dan selalu ini yang digunakan sebagai senjata—adalah izin rumah ibadah. Alasan yang sudah pasti basi, tapi jangan salah, tindakan main usir seperti ini juga mendapat pembenaran legalistik.
Aturan rumah ibadah membenarkan praktik usir-mengusir, serang-menyerang, larang-melarang seperti terjadi di Parepare dan Bekasi itu. Yang berpikir waras pasti sudah dibuat muak oleh jahilnya aksi-aksi intoleransi tersebut.
Orang boleh menyangkal kenyataan itu, dengan berdalil, “kan itu kasuistik.” Faktanya, peristiwa kejahilan seperti contoh dua kasus di atas terjadi secara terus-menerus, acak, dan selalu mewarnai kehidupan keberagaman kita.
Semua peristiwa itu, seperti mengusik kesadaran historis kita, “sebenarnya kita (Indonesia) ini bangsa toleran, atau sebaliknya?”
Berkedok
Menjawab pertanyaan tersebut tidak bisa sembrono. Bila dinyatakan bahwa DNA kita sesungguhnya adalah bangsa toleran, mengapa persekusi terhadap minoritas seperti tidak mau berhenti.
Sebaliknya, bila tergesa-gesa menyatakan DNA kita adalah bangsa intoleran, tentu ini akan menyakitkan hati banyak orang, terutama bagi mereka yang gemar berada di dalam festival keberagaman.
Ada baiknya kita menoleh ke belakang sebentar. Membaca psiko-sosial masyarakat yang bertumbuh secara ambigu, seperti tampak pada kasus-kasus tersuguh di atas. Siapa tahu ambiguitas itu bisa dicari jawabannya dengan memahami akar pembentukan ambiguitas tersebut.
Seorang ahli antropologi kultural berkebangsaan Belanda, Henry Theodore Fischer, pernah melacak ambiguitas itu. Ia meneropongnya jauh dengan memecahkan problem mental sosial anak-anak Indonesia. Ia mendokumentasikan itu dalam Kinderanntal en Kinderleven in Indonesie (1950).
Dalam semua sub-kultur, baik di Batak, Bugis, Jawa bahkan Madura, anak-anak Indonesia bertumbuh dalam sistem pengasuhan yang permisif. Mereka diperkenankan melakukan apa pun, tidak mengenal disiplin, bahkan dalam kadar tertentu tidak mengenal aturan.
Anak-anak dibiarkan berbuat apa saja, baik di rumah maupun di tetangganya. Diperkenankan makan apa pun, tanpa disiplin waktu, sehingga mereka tidak memiliki kedisiplinan atas apa pun, terutama waktu dan hak-hak dasar orang lain.
Meski begitu, pada saat bersamaan anak-anak juga bertumbuh dalam suatu tradisi paternalisme yang sangat kaku, dan merepresi mental mereka. Anak-anak dibiarkan sesukanya, tapi pada saat bersamaan harus patuh pada kepemimpinan bapak yang tak memberi kompromi cuma-cuma.
Anak-anak ini akan tumbuh menjadi pribadi yang egois, tetapi juga rapuh dan frustasi. Kerapuhan ini hampir tidak memberi kemungkinan lain, kecuali merayakan kehidupan komunalisme dan kolektivisme sebagai pelindungnya.
Mereka berkepribadian egois, rapuh, dan tanpa tanggung jawab. Kolektivisme hanya “pelarian” yang paling aman untuk mengamuflasekan egosentrisme. Inilah situasi mental rata-rata yang mengantar anak-anak menuju manusia dewasa.
Bayangkan bila konstruksi mental seperti ini yang membentuk gugusan kehidupan keagamaan di Indonesia. Setiap orang sesungguhnya, bertumbuh sebagai pribadi yang sangat egois dan tanpa tanggung jawab, terutama dalam berurusan dengan kehadiran orang lain (liyan).
Dalam kehidupan sosial yang luas, tentu pribadi-pribadi seperti ini harus tunduk pada platform kebangsaan yang diciptakan oleh negara: toleransi, kerukunan, bhinneka tunggal ika. Maka tidak ada cara lain untuk mengada di ruang sosial bagi setiap individu, kecuali berlindung pada narasi kolektivisme tersebut.
Hanya jangan pernah lupa, itu adalah suatu kamuflase. Kolektivisme dalam narasi toleransi dan kerukunan, adalah sarana berlindung paling aman untuk menyembunyikan mental-sosial rata-rata individu yang dibesarkan dengan pola pengasuhan yang permisif dan eksesif.
Ketika bergerombol dalam jumlah besar, individu-individu seperti ini dengan sesuka hatinya mendirikan tempat ibadah berlipat-lipat banyaknya; menjamur. Dan dalam kadar tertentu, tidak masuk akal.
Meski begitu, karena bertumbuh sebagai pribadi yang rapuh, umumnya mereka sangat sensitif dan terusik dengan satu saja kehadiran rumah ibadah orang lain.
Saya sepenuhnya menyadari tulisan Henry Theodore Fischer adalah warisan antropologi kolonial. Tapi entah mengapa, dalam konteks toleransi yang rapuh di Indonesia, saya merasa mendapatkan banyak insight. Begitulah kira-kira. []