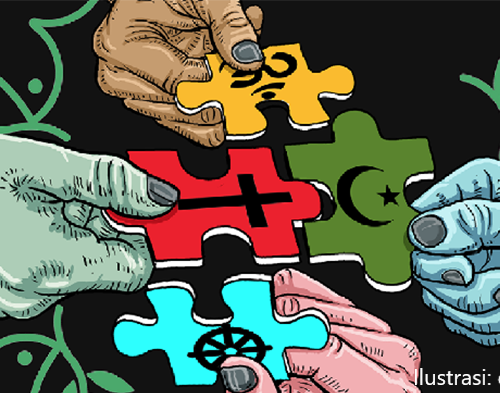Kalau kita belajar sejarah di sekolah, sering kali kita dapati narasi resmi tentang kolonialisme di Indonesia. Narasi ini biasanya penuh dengan heroisme perjuangan kemerdekaan dan menyoroti pahlawan nasional kita.
Meskipun sesungguhnya, menelisik sejarah kolonial Indonesia itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami.
Ada banyak sisi gelap yang tak mudah untuk ditelisik dan diurai karena suatu kepentingan tertentu. Kalau kita mengingat kembali terkait dengan sejarah kolonial maka nuansa nasionalisme akan tampak begitu kental adanya.
Misalnya, kita diajarkan tentang perjuangan pahlawan seperti Diponegoro atau Cut Nyak Dien melawan penjajah Belanda. Tujuannya bagus, biar kita bangga dan menghargai perjuangan mereka.
Masalahnya, narasi ini sering kali simplifikatif atau bahkan menutupi aspek yang tak kalah penting dari sebuah “perjuangan” bangsa dalam merenggut kembali kebebasan individu dan hak asasi manusia.
Benedict Anderson, dalam karyanya yang masyhur, Imagined Communities pernah menyindir bahwa negara acapkali menggunakan (narasi) sejarah sebagai alat untuk membangun dan melegitimasi identitas nasional.
Di Indonesia, narasi resmi sejarah kolonial ini digunakan untuk membantu menciptakan identitas nasional yang kuat. Namun sayangnya, hal demikian sering mengabaikan dan menyederhanakan realitas yang sebenarnya terjadi.
Padahal dalam padangan postkolonialisme, sejarah kolonial itu bukan hanya tentang perang dan kepahlawanan. Ada banyak unsur lain seperti perbudakan, eksploitasi ekonomi, dominasi ideologi dan tentu saja penginjakan hak asasi.
Postkolonialisme tidak hanya mengeksplorasi sejarah kolonialisme, tetapi juga menganalisis bagaimana bekas jajahan menegosiasikan identitas mereka dan merespon sisa-sisa dominasi kolonial dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang lebih luas.
Pandangan ini akhirnya bisa digunakan untuk memotret banyak hal mulai dari lahirnya identitas hibrida (hybrid identities), orientalisme, resistensi dan emansipasi, serta dekolonisasi pengetahuan.
Dalam konteks Indonesia, sejarah kolonial tidak hanya meninggalkan luka mendalam tentang dominasi fisik atau perebutan tanah air melainkan juga tentang—meminjam istilah Frantz Fanon (psikolog dan filsuf)—bagaimana kolonialisme merusak identitas dan kesadaran diri subyek kolonial, serta menyerukan kekerasan revolusioner sebagai jalan menuju pembebasan dari kolonialisme.
Sistem tanam paksa (Cultuurstelsel) yang diprakarsai oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada abad ke-19 adalah salah satu contoh eksploitasi ekonomi dan penindasan yang sering luput atau tak begitu dieksplorasi lebih mendalam di sekolah.
Pada masa itu, petani dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi dan gula dengan harga yang sangat rendah, yang membuat mereka menderita kelaparan dan kemiskinan.
Bahkan tidak hanya itu, tanam paksa—meminjam istilah Karl Marx—juga representasi keserakahan kapitalisme yang cenderung mengeksploitasi kelas pekerja untuk keuntungan penguasa.
Bagi kolonial, bangsa jajahan itu dianggap masyarakat kelas dua dan tak mampu menentukan nasibnya sendiri lantaran tidak mengerti tentang pengetahuan. Hal ini menjadi tak aneh jika Anda pernah membaca buku Edward Said yang terkenal berjudul Orientalism itu.
Edward Said dalam buku tersebut mengkritik dengan lantang cara Barat yang coba mengkonstruksi citra Timur melalui lensa yang subyektif dan merendahkan. Ia berargumen bahwa pengetahuan ini digunakan sebagai alat kekuasaan untuk membenarkan dominasi kolonial.
Maka Perang Diponegoro (1825-1830) maupun Perang Aceh (1873-1904) misalnya, harus dipahami bukan hanya sekadar merebut kembali kemerdekaan tapi juga—menyitir padangan Max Weber—sebagai kulminasi dari rasa muak dan kesengsaraan atas penindasan dan ketidakadilan yang sudah tak mampu dibendung lagi.
Lagipula tuduhan orientalisme bahwa bangsa Timur khusususnya Indonesia yang bodoh itu juga tak bisa dibenarkan.
Mereka lupa bahwa filsuf Barat sendiri taruhlah, Betrand Russel, justru menepis itu dengan berargumen bahwa tak ada manusia yang lahir bodoh. Manusia terlahir dalam kondisi belum tahu (ignorance).
Maka seyogianya kita perlu mengamini pendapat dari salah satu sejarawan Indonesia, Sartono Kartodirdjo, yang mengatakan bahwa dalam melihat sejarah kolonial haruslah dengan perspektif yang lebih luas agar kita benar-benar bisa memahami sampai ke akarnya.
Negara lewat instrumen pemerintah juga harus menampilkan sisi lain dari sejarah kolonialisme dengan cara yang lebih komprehensif dan mendalam.
Sebab ada banyak sisi lain yang tak banyak orang tahu tentang misalnya bagaimana suara kelompok terpinggirkan, terutama perempuan di bekas koloni, seringkali diabaikan atau disalahpahami baik oleh struktur kolonial maupun diskursus intelektual Barat.
Setidaknya begitulah gambaran Gayatri Chakravorty Spivak dalam bukunya Can the Subaltern Speak? yang menarik dan seringkali dijadikan sebagai “pegangan” baik aktivis perempuan maupun para peminat kajian postkolonial.
Dus, postkolonialisme, secara keseluruhan, mengajak untuk memahami dan menganalisis warisan kolonialisme yang kompleks dan berkelanjutan, serta memperjuangkan keberagaman suara dan pengalaman dalam sejarah narasi global. []