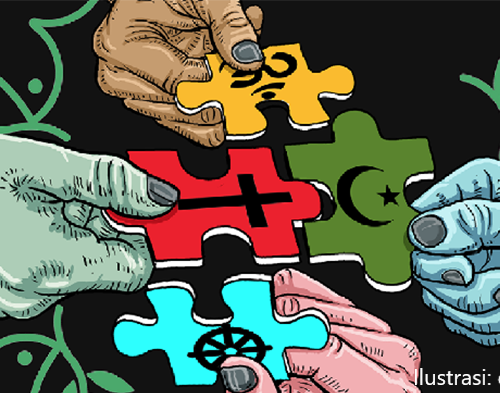Sebelum dibahas lebih lanjut, terlebih dulu kita akan kupas terminologi “dinamisasi”, dan “ide atau gagasan” serta hubungan keduanya. Barangkali penggunaan konsep tersebut masih asing oleh kita dan akan menghadapi hambatan nantinya.
Menurut pandangan Gus Dur, dinamisasi pada dasarnya mencakup dua proses: revitalisasi nilai-nilai hidup positif yang telah ada, di samping mencakup pula pergantian nilai-nilai lama itu dengan nilai-nilai baru yang dianggap lebih sempurna. Lebih lanjut, kata dinamisasi itu sendiri, dalam penggunaannya akan memiliki konotasi perubahan ke arah penyempurnaan keadaan dengan menggunakan sikap hidup, serta peralatan yang telah ada sebagai dasarnya (Gus Dur, 1971).
Sedangkan konsepsi tentang ide, John Locke—filsuf Inggris pakar empirisme itu—memaknainya secara luas. Menurutnya, ide menggantikan apa saja yang merupakan obyek pengertian sewaktu orang (sedang) berpikir. Dalam istilah itu, ia masukkan term fantasma, paham, spesies atau apa saja yang dapat dipakai oleh pikiran dalam aktivitas berpikir.
Locke membedakan antara ide-ide simple dan kompleks. Ia membicarakan tiga jenis ide kompleks: “modus,” “substansi,”dan “relasi.” Karena ide kompleks mana pun dapat dihasilkan dengan menjalankan data inderawi, doktrin tentang ide bawaan pun ditolak (Lorens Bagus, 2000).
Dalam sebuah ide atau gagasan yang muncul tak lepas dari kritik. Dalam ranah keilmuan filsafat dan ilmu sosial, muncul berbagai macam pandangan tentang kritik. Sindhunata misalnya, mengartikan kritik sebagai aktivitas pembebasan. Dalam pengertian Kantian, kritis berarti kemampuan subyek untuk melepaskan diri, dan mengambil jarak dari obyek.
Media massa kini semakin berkurang sisi kritisnya lantaran salah satunya disebabkan oleh terlalu dominannya konsumsi popular dalam konteks industri budaya kapitalisme “akhir.”
Sedangkan Hegel, mengartikan kritis sebagai kemampuan obyek untuk membangun kemampuan sintesis dengan menyatakan dirinya dalam obyek. Marx pada selanjutnya menyebut bahwa, kritis sebagai kemampuan manusia merealisasikan dirinya dalam obyek itu.
Singkatnya, kritis berarti kemampuan penyadaran diri manusia dari kekuatan hegemonik tertentu sehingga pada gilirannya manusia itu mampu melakukan perlawanan dan pengubahan atas dirinya (Faruk, 1997).
Pertanyaannya kemudian, apa yang terjadi ketika sebuah ide atau gagasan dibenturkan dengan realitas? Dalam konteks budaya, kritik adalah suatu pengukuhan eksistensi sebagai sebuah institusi sosial yang lahir dari kebutuhan pengembangan hidup bersama manusia.
Maka homologi manusia dipahami sebagai makhluk yang parsial, artinya manusia haruslah dipahami dalam realitas keanekaragamannya (Kaelan, 1998). Pun juga dengan realitas. Sebagai hasil konstruksi kolektif yang mengalami proses tertentu, realitas menjadi sesuatu yang seakan eksternal, dan obyektif (realitas sosial).
Baca juga: https://diskursusinstitute.org/2020/08/22/gus-baha-dan-penyegaran-kembali-pemahaman-islam/
Oleh sebab itu, definisi tentang realitas tak akan pernah berdiri sendiri. Ia membutuhkan legitimasi baik dari luar maupun dari dalam diri manusia demi kekokohan dirinya sendiri (Faruk, 1997). Tawarannya adalah dengan ide dan gagasan serta kritik yang terbuka akan membangun realitas serta budaya kritis.
Untuk mewujudkan itu, mari kita ingat kembali bahwa dalam tradisi teori kritis setidaknya ada dua hal yang menjadi sorotannya: media dan budaya massa. Budaya pop (pop culture) menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam konteks masyarakat kontemporer.
Ia meliputi banyak hal termasuk bagaimana ideologi dipandang tak lagi penting. Itu salah satunya juga disebabkan menjamurnya media yang semakin kemari kian bebas. Media sosial adalah salah satu contohnya saat ini.
Adorno dan Horkheimer—sebagai generasi awal Mazhab Frankfurt—mengategorikan budaya massa dalam konteks apa yang mereka sebut sebagai kapitalisme “akhir.” Mereka menawarkan analisis produksi budaya yang menetapkan peran dan fungsinya dalam kapitalisme pada masanya dan memberinya konteks historis dengan memberikan penjelasan tentang kemunculan kapitalisme itu sendiri, dan peran budaya yang semakin berpengaruh di dalamnya (Paul A. Taylor & Harris, 2008).
Oleh sebab itu tak aneh bila misalnya, media massa kini semakin berkurang sisi kritisnya lantaran salah satunya disebabkan oleh terlalu dominannya konsumsi popular dalam konteks industri budaya kapitalisme “akhir” itu tadi. Dialektika gagasan atau ide dalam hal ini menjadi semakin buram. Dan masyarakat lebih memilih “berebut wacana” di ruang digital, khususnya media sosial.
Celakanya, ruang publik digital menyediakan panggung “sebebas-bebasnya” proses silang sengkarut gagasan tanpa disertasi oleh kapasitas kelimuan dan data yang mumpuni. Akibatnya, hoaks seolah menjadi bagian dari arus lalu lintas digital yang (seolah) sulit dibedakan dibendung. Parahnya lagi, kritik dalam konteks ini seringkali berujung kepada caci-maki, dan jeruji besi.
Lantas bagaimana gagasan (dianggap) bernilai? Dalam hal ini tersedia tiga kemungkinan pilihan: pertama, sikap masalah nilai. Sebab nilai menyangkut sikap seorang individu. Jika seorang individu memiliki sikap maka ia seharusnya paham soal nilai. Kedua, sikap tersebut bersangkutan dengan sesuatu yang tidak hakiki. Dalam pengertian sikap seperti ini ditimbulkan oleh suatu kualitas nilai, tetapi bukan dari hakikatnya. Ketiga, sikap adalah sumber pertama serta ciri yang tetap dari segenap nilai. Artinya bila saya mengatakan “x” bernilai, maka dalam arti yang sama saya dapat mengatakan “Saya mempunyai kepentingan pada x” (Louis O. Kattsoff, 1996).
Demikianlah secara ringkas telah dikemukakan tentang dinamisasi gagasan dan tentang budaya kritis. Setidaknya gambaran singkat dalam esai ini bisa menjadi penyadaran tentang bagaimana arah baru sebuah gagasan berkembang dan mempunyai nilai sesuai dengan kreativitas kita masing-masing.
Walaupun tulisan ini tidak membicarakan sarana-sarana ilmiah yang komprehensif, bukan berarti ini merupakan akhir. Dengan kata lain, esai singkat ini adalah pengantar awal untuk perdiskusian lebih lanjut yang terbuka dan bebas dari intimidasi serta dominasi ideologi. Sehingga pada praktiknya, gagasan yang dinamis itu mampu benar-benar membawa perubahan yang nyata. Semoga saja. []