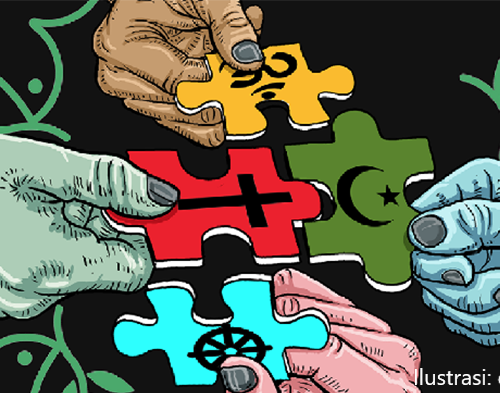Tanah merupakan suatu topik wacana yang telah mewarnai beragam diskursus dalam lintasan sejarah kehidupan manusia. Dari tradisi-tradisi kuno mengenai asal-usul manusia hingga percakapan dunia “modern” hari ini, tanah hampir selalu menjadi bagian penting.
Signifikansi tanah bagi kehidupan tidak hanya membuatnya ‘disyukuri’ tetapi juga menjadi rebutan, baik sebagai ruang hidup maupun sebagai entitas bernilai. Kasus sengketa lahan, konflik tanah adat, dan persoalan ekologis seperti perusakan tanah akibat pembabatan hutan adalah sebagian kecil yang dapat menggambarkan terjadinya kontestasi atas tanah.
Paradigma mengenai tanah terang saja menjadi faktor penentu dalam persoalan ini. Masalah-masalah yang disebutkan di atas misalnya paling banyak disebabkan oleh perspektif yang melihat tanah sebagai sekadar obyek untuk pemenuhan kebutuhan, atau bahkan hasrat, manusia.
Untungnya, masih banyak paradigma-paradigma yang lebih bijaksana dalam melihat tanah sebagai subyek yang bernilai pada dirinya sendiri. Bahkan memiliki signifikansi religius, sejauh agama atau religiusitas dipahami sebagai yang orientasinya adalah untuk merawat kehidupan yang melingkupi manusia, makhluk hidup lainnya, bumi, dan bahkan semesta.
Cara pandang terhadap tanah yang paling bermasalah saat ini adalah melihatnya sekadar sebagai kapital ekonomi demi kepentingan produksi yang sering kali dialibikan untuk kepentingan (bersama) manusia.
Akibatnya, tanah dikeruk dan dirusak, singkatnya “diperkosa,” untuk memuaskan hasrat kapitalisme belaka. Hutan dan biodiversitasnya yang meliputi bhineka flora dan fauna serta manusia, terutama masyarakat adat, menjadi subyek yang terdampak secara langsung dan signifikan.
Dalam hubungan antarsubyek, manusia memegang komitmen untuk merawat interrelasi antara manusia dan alam. Sebagai masyarakat yang seluruh aspek kehidupannya berkaitan erat dengan alam, tanah merupakan subyek signifikan bagi mereka.
Sayangnya, perspektif keliru ini terus-menerus direproduksi dan bahkan diperkuat dengan berbagai macam dalil, pembangunan ekonomi tidak boleh dihambat oleh pertimbangan ekologis misalnya. Kuasa dari pihak-pihak yang berkepentingan menjadi backing-kuat bagi perkembangan dan langgengnya narasi-narasi yang kini menjadi taken for granted ini. Manusia akhirnya dibuat lupa tentang nilai-nilai luhur yang sebenarnya sudah ada dan begitu kuat dalam lintasan sejarah peradaban manusia.
Tanah, Ekologi dan Agama
Dalam beberapa dekade terakhir ini, terutama setelah menguatnya diskursus ekologi di tahun 1960an, memang banyak muncul wacana yang menarasikan kembali nilai intrinsik dari alam termasuk tanah. Ia tidak lagi dilihat sebagai yang nilainya selalu bergantung pada manusia, yaitu sebagai kebutuhan, tetapi bernilai pada dirinya sendiri. Alih-alih bergantung pada manusia dan menjadi obyek semata, hubungan manusia dan tanah adalah interdependensi dan intersubyektif.
Namun, sejak semula sebenarnya kesadaran ini sudah melekat kuat dalam worldview peradaban manusia sebagaimana tergambar dalam kosmologinya, mitos-mitos, dan bahkan tradisi keagamaan seperti kitab suci. Dalam Perjanjian Lama misalnya, tanah sudah menjadi topik sentral sejak awal mula penciptaan hingga perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian.
Manusia diciptakan dari tanah, diberi ruang hidup di atas tanah bersama jutaan flora dan fauna yang ada, hingga tanah menjadi penanda identitas baginya. Perjalanan panjang bangsa Israel adalah demi tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah dalam hal ini menjadi tanda perjanjian antara manusia dan Tuhan.
Melihat tanah sebagai subyek merupakan narasi sekaligus resistansi terhadap narasi-narasi destruktif yang mengkapitalisasi tanah sebagai properti. Paradigma intersubyektif ini berkembang dalam wacana akademik, aktivisme, hukum, dan keagamaan. Dalam paradigma hukum, salah satu milestone dalam diskursus ini misalnya buku berjudul Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment karya Christopher D. Stone.
Gebrakan karya Stone tersebut adalah disrupsinya terhadap paradigma hukum mengenai manusia sebagai satu-satunya yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga dalam kasus perusakan hutan misalnya, pohon-pohon tidak dapat menggugat ke pengadilan untuk mengklaim haknya untuk tumbuh.
Pertanyaannya, apakah pohon memiliki hak tersebut dan bagaimana pohon bisa hadir di pengadilan untuk mengadukan kasusnya? Dalam hal ini, Stone berargumen bahwa pohon atau lingkungan semestinya juga diberikan hak legal, sebuah argumen yang tentu banyak ditertawakan di era itu bahkan hari ini.
Stone mendasarkan argumentasinya pada proses-proses berkembangnya paradigma hukum itu sendiri. Sebelumnya, mereka yang memiliki kedudukan hukum sangatlah eksklusif, banyak kelompok seperti perempuan atau bahkan termasuk laki-laki dengan latar belakang tertentu yang tidak memilikinya. Namun kemudian dalam perkembangannya, kini perempuan dan banyak kelompok lain sudah diakui status legalnya.
Dengan demikian, paradigma tentang siapa yang memiliki legal standing ini dapat dan mesti terus diperluas, dalam hal ini, untuk juga mencakup pohon atau alam. Mereka tentu tidak bisa hadir di pengadilan, tapi dengan status hukumnya, mereka bisa diadvokasi dan pertahankan. Argumentasi ini tentu saja tidak utopis sebab di beberapa negara, memberi status legal pada alam sudah dilakukan, Te Urewera di New Zeland misalnya.
Sekali lagi, paradigma semacam ini mestinya tidak asing bagi kita, jika saja kita tidak dialienasi darinya. Dalam paradigma agama leluhur, yang masih dihidupi hingga kini oleh ragam penghayat kepercayaan dan masyarakat adat di Indonesia dan dunia misalnya, alam termasuk tanah dilihat sebagai subyek non-manusia dalam kosmologi intersubyektif.
Dalam hubungan antarsubyek ini, manusia memegang komitmen untuk merawat interrelasi antara manusia dan alam. Sebagai masyarakat yang seluruh aspek kehidupannya berkaitan erat dengan alam, tanah merupakan subyek signifikan bagi mereka.
Tanah tidak mereka “miliki” sebagai properti dengan bukti administratif seperti sertifikat karena bukan merupakan obyek. Sistem kultural, ekonomi, dan keagamaan mereka saling berkelindan dalam keterhubungan mereka dengan alam dimana mereka hidup, melakukan ritual, dan merawat kehidupan.
Dalam hal ini, keberagamaan mereka tidak hanya dalam kaitannya dengan ritual dan hubungan dengan subyek-subyek transenden, melainkan paralel dengan praktik-praktik kehidupan secara menyeluruh termasuk di dalamnya entitas materil seperti alam dan tanah.
Jika pandangan dominan hari ini cenderung mendikotomi tindakan religius yang hierarki dari “bumi” ke “langit” dan tindakan kultural yang horizontal di dunia, paradigma agama leluhur tidak menganut dikotomi tersebut. Menjaga alam misalnya adalah tindakan ekologis yang bersifat kultural sekaligus religius. Justru dalam tindakan-tindakan dan worldviews yang ekologis itulah mereka merawat komitmen keberagamaannya.
Dalam wacana ini, fakta bahwa kata agama atau religion adalah istilah yang datang kemudian dalam tradisi agama leluhur penting untuk dicatat karena dalam istilah tersebut sudah inheren dikotomi antara yang ‘sakral’ dan yang ‘profan.’ Tanah dalam dikotomi ini adalah entitas profan. Padahal, dalam kosmologi agama leluhur, setiap subyek termasuk tanah memiliki signifikansi yang padanya dan darinya komitmen intersubyektif mesti dirawat.
Dalam konteks krisis ekologis yang semakin mengkhawatirkan, paradigma semacam ini, yang umumnya dikategorikan sebagai paradigma keagamaan, semakin diakui signifikansinya. Sebabnya, S. H. Nasr misalnya melihat krisis ekologis secara paralel dengan krisis spiritual. Sikap dan tindakan manusia terhadap alam ditentukan oleh paradigma yang dimilikinya.
Salah satu faktor penting dalam pembentukan paradigma ini adalah tradisi kultural-keagamaan seperti paradigma agama leluhur di atas. Jika alam sudah diprofanisasi dan diobyektifikasi sehingga kehilangan nilai intrinsiknya, maka tradisi-tradisi ini menjadi sangat penting perannya dalam merekonstruksi cara manusia mempersepsi dan bertindak terhadap alam termasuk tanah. []