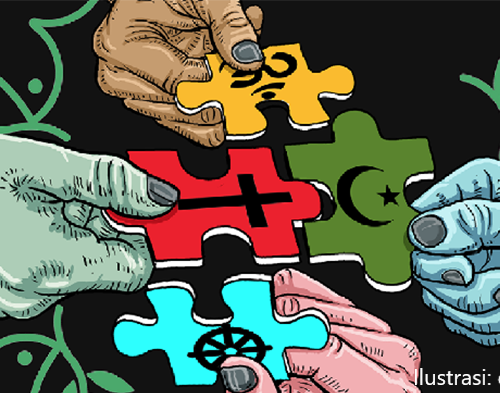Persoalan kekerasan seksual yang menimpa kaum perempuan seperti tiada habisnya. Baru-baru ini, sebuah lembaga pendidikan Islam (modern) bernama Madani Boarding School di Kota Bandung Jawa Barat menjadi biang keladi atas kasus rudapaksa puluhan santriwati yang dilakukan oleh gurunya. Perbuatan keji yang mengakibatkan kehamilan itu sontak membuat publik gempar.
Sumpah serapah, dan kutukan yang ditujukan kepada pelaku pun berseliweran di media sosial. Semua geram, dan tentu saja tak habis pikir atas kejadian tersebut. Menariknya, dari hasil selancar penulis di beberapa platform media sosial, tak ada satupun komentar netizen yang mengarah pada penyudutan atau subordinasi kepada perempuan sebagai korban. Biasanya ketika muncul kasus pemerkosaan yang menimpa perempuan akan muncul narasi-narasi semacam, “penyudutan perempuan” agar menjaga penampilan, menutup aurat, dsb.
Sehingga publik akan mengambil kesimpulan sepihak bahwa kasus pemerkosaan itu yang salah adalah perempuan, bukan laki-laki yang memperkosanya. Lantas bagaimana jika kejadian itu terjadi di lingkungan pendidikan Islam? Apakah karena perempuan tidak menutup aurat, ataukah memang karena nafsu, dan kesempatan itu memang tidak mengenal agama apa pun? Artinya siapa pun bisa menjadi pelaku maupun korban.
Cara pandang yang bias gender semacam itu memang masih seringkali kita temukan di lingkungan kehidupan sehari-hari. Bahkan kalau kita membaca hasil survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA), setidaknya 17 persen korban pelecehan seksual itu justru mereka yang mengenakan pakaian tertutup (detikNews/2019).
Lebih dari itu, seiring perkembangan dunia digital yang luar biasa ini, kekerasan seksual terhadap perempuan pun meningkat di dunia maya. Humas Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) mencatat bahwa kekerasan seksual berbasis online diestimasi meningkat lebih dari 40 persen pada tahun ini. Pada tahun 2019, ada 281 kasus yang tercatat, dan yang menjadi sasaran dalam kasus tersebut adalah generasi muda terutama perempuan dengan indeks 71 persen.
Dengan menggunakan paradigma tauhid, Qur’an mendasarkan doktrin kesetaraannya secara universal tanpa memandang, suku, ras, gender, dan lain sebagainya.
Salah satu penyebab kekerasan seksual yang semakin merajalela adalah lambannya penegakan hukum, dan belum adanya regulasi yang memadai untuk mengantisipasinya. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pun sampai saat ini juga masih sekadar wacana belaka.
Makanya tak heran jika beberapa waktu lalu muncul tagar #percumalaporpolisi# kemudian disusul dengan #indonesiadaruratakhlak# di lini Twitter lantaran kejengahan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum yang terkesan lamban.
Selain itu, dalam konteks kekerasan seksual yang menjadikan dalil agama (Islam) sebagai media untuk meneguhkan otoritas pelaku untuk melancarkan misi keji itu, kiranya perlu disemarakkan wacana tentang studi gender dan feminisme Islam. Salah satu tokoh yang bisa dijadikan rujukan adalah Amina Wadud.
Sebagai seorang intelektual, dan feminis Muslim, Wadud telah memberikan sumbangsih pemikiran luar biasa terhadap diskursus tafsir Qur’an yang tidak bias gender. Dalam salah satu karyanya, Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective, Wadud telah berhasil memberikan penyegaran, dan menyingkirkan bayang-bayang tafsir, dan pemikiran Islam yang patriarkis selama empat belas abad lamanya.
Dengan menafsirkan ulang teks-teks Qur’an menggunakan kacamata hermeneutika, atau dalam istilah Wadud “hermeneutika tauhid,” ia menyakini bahwa kesatuan Qur’an itu menyeluruh. Artinya, dengan menggunakan paradigma tauhid, Qur’an mendasarkan doktrin kesetaraannya secara universal tanpa memandang, suku, ras, gender, dan lain sebagainya.
Gerakan progresif yang dilakukan oleh Wadud ini boleh dibilang cukup sukses. Ia mampu membongkar teks-teks Qur’an yang ditafsirkan secara berat sebelah, dan cenderung memojokkan kaum perempuan yang berakibat pada pembatasan gerak di ruang publik, termasuk kekerasan seksual.
Dengan demikian, pemaknaan Qur’an seperti yang diperjuangkan oleh Wadud tersebut, merupakan bukti konkret betapa Qur’an sesungguhnya menjamin kesetaraan, dan mengutuk segala bentuk ketidakadilan. Setidaknya, hal demikian bisa sedikit memperbaiki wajah buram sejarah yang mengafirmasi ketidakadilan, bahkan dilakukan secara legal oleh komunitas Muslim.
Cara pandang yang terbuka ini seyogianya diajarkan di setiap pondok (pesantren) yang ada di Indonesia khususnya, dan semua perempuan pada umumnya. Agar tidak ada lagi kekerasan seksual dengan dalih agama. Apalagi perkara gender adalah tentang konstruk budaya. Ini bisa menjadi sangat riskan jika dimanfaatkan oleh oknum, dan dikawinkan dengan otoritas tertentu.
Inilah jihad sesungguhnya yang harus terus digelorakan. Tentu saja dibutuhkan kerjasama, dan kehadiran negara sebagai bentuk perlindungan kepada warganya. Jangan sampai pameo “viral dulu baru ditindak” terus memenuhi lini media massa.
Sebab jika itu dibiarkan, maka kepercayaan (trust) publik terhadap pemerintah dan penegak hukum akan semakin luntur. Sebab pelecehan seksual sekecil apa pun adalah suatu bentuk penistaan harkat, dan martabat manusia. Apalagi jika menjadikan agama sebagai legitimasinya.
Bagaimanapun, lembaga pendidikan Islam adalah ruang pembentukan karakter yang mengendepankan nilai-nilai islami, bukan ruang yang bebas untuk praktik monopoli oleh ustaz ataupun kiai terhadap santriwan-santriwati. []