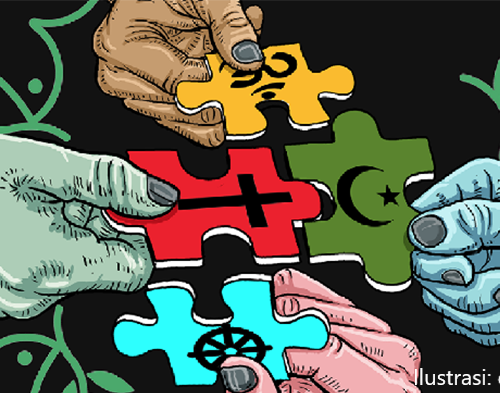Kemajuan teknologi-informasi yang kian pesat telah membawa kita masuk ke dalam era digital seperti saat ini. Sebuah era baru yang ditandai dengan distribusi informasi yang dapat dilakukan secara cepat, dan mudah melalui berbagai platform. Kemudahan untuk mengakses informasi ini, kemudian dimanfaatkan manusia untuk mengakses apa pun, tak terkecuali wacana, artikel ilmiah dan informasi tentang praktik-praktik keagamaan.
Oleh karena itu, tidak aneh jika Generasi Z (mereka yang lahir pasca tahun 1995) lebih senang belajar agama dari internet ketimbang datang ke surau, madrasah, atau pesantren. Tentu saja salah satu alasannya adalah faktor instanitas. Setidaknya itu menurut hasil Survey Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta bertajuk, “Api dalam Sekam: Keberagamaan Muslim Gen-Z” (2018).
Transformasi penyampaian informasi ini tidak hanya dipengaruhi oleh berubahnya kebutuhan manusia akibat pertumbuhan teknologi, tapi juga dipengaruhi oleh disrupsi digital. Rhenald Kasali dalam opininya di Jawapos (2021) menjelaskan bahwa, disrupsi ini bagaikan arus deras sungai yang menantang, akan tetapi secara bersamaan menawarkan kesempatan yang lebih besar dan setara. Maka tak mengherankan jika kemudian banyak arus informasi lahir, dan berharap mendapatkan keuntungan secara langsung maupun tidak langsung dari era disrupsi ini.
Dalam konteks ilmu agama, kita dapat dengan mudah menemukan berbagai website dengan macam-macam branding yang menawarkan informasi aktual yang sedang banyak dibicarakan orang. Sayangnya, era disrupsi ini tidak menilai kualitas informasi sebagai standar untuk memberikan kesempatan bertumbuh pesat. Algoritma, kata kunci dan frekuensi klik menjadi lebih penting ketimbang kualitas dan kredibilitas informasi. Hal ini juga yang memengaruhi ragam interpretasi terhadap sumber hukum agama tersebar luas, dan dijadikan sumber rujukan oleh banyak orang.
Hal ini sebenarnya sudah diprediksi lama. Pada awal abad 20, seorang ahli media dan kritikus budaya dari Amerika bernama Neil Postman, menulis buku cukup menarik bertajuk, Technopoly: The Surrender of Culture to Technology. Postman melihat potensi teknologi sebagai aras pembodohan lantaran memonopoli berbagai aspek kehidupan, terutama budaya. Akibatnya, kebenaran menjadi kabur maknanya, alih-alih coba memperjelas diskursus keagamaan, seringkali teknologi malah menggeser penikmatnya untuk mengonsumsi hal ihwal yang hanya berbau klimaks visual belaka dan melupakan substasinya.
Ketika narasi yang dibawa telah mendapatkan target pasar yang tepat, dengan mudah fanatisme buta tercipta, sehingga hanya dengan berbekal bacaan dari konten A, netizen bisa menuduh macam-macam konten B tanpa pernah menyadari bahwa dirinya sedang—meminjam istilahnya Marx—terjebak dalam kesadaran palsu (falsches Bewuβtsein) akibat polarisasi tadi.
Kolaborasi antara demokratisasi ilmu yang meninggalkan kualifikasi dan algoritma media sosial yang membentuk polarisasi tersebut, pelan-pelan telah menggiring banyak orang menuju jurang populisme agama, yang merupakan salah satu ciri utama post-truth era.
Secara sederhana, kamus Oxford pada tahun 2016 mendefinisikan post-truth sebagai sebuah situasi di mana kebenaran parsial versi individu atau kelompok menjadi lebih penting dibandingkan narasi yang sudah mapan atau kebenaran obyektif yang membawa banyak fenomena baru, termasuk populisme agama.
Akibatnya, narasi agama tidak lagi didasarkan pada ushul fikihnya (pondasi legal formal), tetapi pada kepentingan orang yang menarasikannya (author), dan yang paling mudah dinarasikan untuk kepentingan tertentu adalah unsur-unsur ritual, hukum positif serta standar etis dari pola spiritualitas tertentu.
Itulah sebabnya kita lebih sering melihat media sosial bernapaskan islami cenderung pada pembahasan yang dangkal dan dogmatis. Syahdan, hal ini mereka lakukan dengan alibi “untuk mempermudah” secara efisien penikmat konten atau produk sosial media tersebut untuk lebih memahami agama dengan cepat dan instan.
Sumbangsih post-truth terhadap metode dakwah dan pendidikan agama memang tidak dapat dibantah. Post truth tampil sebagai sebuah meta-narasi yang memperlihatkan visi kultural dari suatu kebudayaan atau narasi tertentu. Kultur keilmuan Islam di Indonesia yang sebelumnya terkesan otoritatif, eksklusif dan mengedepankan relasi patron seperti di pesantren perlahan memudar. Dalam bahasa sederhana, orang lebih gemar mondok di internet daripada langsung ke ahlinya.
Post-truth meningkatkan gelombang populisme agama yang semakin menguat dan membawa berbagai dampak yang kontra produktif terhadap perkembangan informasi keagamaan. Beberapa dampak yang mulai dapat kita rasakan saat ini di antaranya:
Pertama, simplifikasi permasalahan menggunakan interpretasi dalil agama. Permasalahan ini kerap kali muncul di media sosial ketika seseorang atau golongan tertentu mengalami permasalahan yang dalam kaca mata fikih klasik masih tergolong langka. Tak butuh waktu lama, biasanya akan bermunculan para komentator yang memberikan potongan ayat kemudian mengatakan “dalilnya sudah jelas” atau sebaliknya, justru mengolok-olok dengan landasan “tidak ada dalilnya”.
Kedua, masih berhubungan erat dengan simplifikasi, yaitu lahirnya pengetahuan parsial tentang suatu praktik ibadah atau relasi sosial yang mengabaikan konteks. Misalnya platform media sosial yang gencar mengampanyekan poligami dengan keyakinan bahwa berpoligami adalah jalan yang baik untuk mengikuti sunnah nabi.
Narasi semacam ini dengan cepat dan mudah dipahami, akan tetapi juga dengan cepat kehilangan konteksnya. Ayat yang biasa digunakan untuk menjustifikasi tindakan ini adalah QS. An-Nisa ayat 3 yang pada saat diturunkan adalah justru untuk membatasi kelakuan jahiliah bangsa Arab yang menikahi perempuan tanpa batas.
Ketiga, fanatisme atau fasisme religius terhadap suatu tokoh atau golongan tertentu yang berujung kepada kejumudan. Sebelum memasuki era digitalisasi informasi, kejumudan sudah banyak terjadi akibat minimnya pengetahuan masyarakat tentang agama yang mereka yakini. Perbedaannya, kejumudan pada era digital ini justru terjadi akibat kolaborasi antara demokratisasi ilmu agama dengan polarisasi yang tercipta di media sosial.
Berbekal branding yang meyakinkan atau konten-konten yang menarik perhatian, seseorang atau kelompok tertentu dengan mudah mendapatkan panggung dan dijadikan rujukan oleh warganet, dengan ataupun tanpa kualifikasi keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika narasi yang dibawa telah mendapatkan target pasar yang tepat, dengan mudah fanatisme buta tercipta, sehingga hanya dengan berbekal bacaan dari konten A, netizen bisa menuduh macam-macam konten B tanpa pernah menyadari bahwa dirinya sedang—meminjam istilahnya Marx—terjebak dalam kesadaran palsu (falsches Bewuβtsein) akibat polarisasi tadi.
Keempat, risiko terjadinya kejahatan atas nama agama. Sudah berapa banyak kasus kekerasan seksual, dan hal eksploitatif lainnya yang dilegitimasi oleh seseorang menggunakan dalih agama?
Belum lama ini, seorang perempuan yang berniat memperdalam ilmu agama hingga mengambil keputusan untuk bersedia menikah siri dengan gurunya kemudian melaporkan kekerasan seksual yang menimpanya. Bahayanya lagi, masyarakat yang terlanjur percaya oleh narasi yang ditampilkan oleh sang “guru” akan cenderung mempertanyakan dan menyalahkan keputusan korban dengan argumen bahwa sang guru memiliki ilmu agama yang tinggi sehingga tidak mungkin berbuat zalim.
Selain keempat efek samping disrupsi digital yang tersebut di atas, narasi agama yang berubah menjadi gelombang populisme agama mungkin juga akan melahirkan mafsadat (kerusakan) lain di kemudian hari jika gelombang informasi terkait agama tetap bebas dinarasikan oleh siapa saja tanpa otoritas keilmuan apa pun. Pasalnya, seperti yang sempat saya singgung di awal, bahwa pada era disrupsi digital, slogan “content is the king” adalah nyata adanya.
Di sisi lain, pihak-pihak yang memiliki otoritas keilmuan untuk menyampaikan hal-hal terkait praktik keagamaan, justru menemui kesulitan. Hal ini masuk akal karena biasanya digitalisasi yang banyak diminati, erat kaitannya dengan simplifikasi. Hal ini tidak mudah dilakukan oleh lembaga keilmuan Islam yang kredibel seperti pesantren. Meskipun sudah ada beberapa pesantren yang mulai adaptif dengan perkembangan teknologi.
Untuk itu, lembaga-lembaga otoritatif terkait, perlu menciptakan sistem penyebaran ilmu dengan cara baru yang tetap menarik perhatian masyarakat awam, tetapi tanpa harus terjebak pada simplifikasi, dan reduksi substansi.
Selain itu, penting juga untuk tetap setia berpegang kepada sanad keilmuan. Sebelum mengenyam informasi, perlu ditelisik keahlian seseorang pada bidang yang ia bicarakan supaya tidak terjebak pada pusaran polarisasi dunia digital.
Meminjam istilah Nadirsyah Hosen, Saring Sebelum Sharing. Artinya, dalam mengakses informasi keagamaan, perlu adanya tabayyun (verifikasi), dan peningkatan kapasitas keilmuan agar tidak cepat mengklaim kebenaran tunggal atas suatu interpretasi dalil agama. []