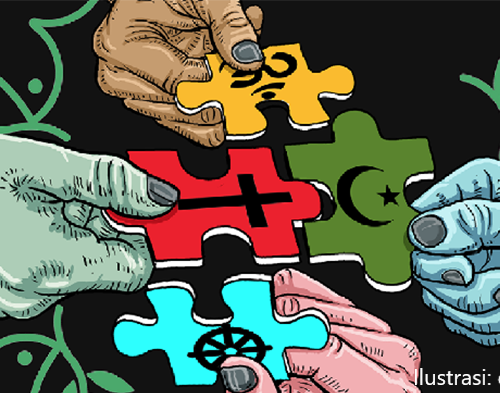Agama (dan) kebudayaan rasanya sungguh sulit dipisahkan. Kata ‘sulit’ perlu digunakan untuk menunda pemaknaan yang lebih radikal: agama-kebudayaan adalah satu kesatuan. Dua istilah ini hampir memiliki rujukan praktik empiris yang serupa.
Namun, mengapa ia seakan-akan dipahami sebagai dua hal yang berbeda? Setelah dibedakan, mengapa pula ia selalu dikaitkan satu sama lain (umumnya menggunakan konjungsi ‘dan’)? Dipisah total seperti tak bisa, mau disatukan terlanjur dianggap berbeda. Dalam pemaknaan yang umum di Indonesia, definisi agama dikokohkan dengan elemen-elemen inti seperti doktrin tentang Tuhan (harus Esa), kitab suci, Nabi, dan pengikut.
Sementara itu, kebudayaan (kadang disamakan dengan tradisi) dikaitkan dengan praktik hidup di masyarakat yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Kendati demikian, tak jarang praktik kebudayaan secara inheren memiliki nilai spiritual layaknya agama. Jadi, sebenarnya bagaimana relasi antara agama (dan) kebudayaan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kiranya penting untuk menelaah ulang konsep mengenai ‘agama’ dan ‘kebudayaan.’
Reifikasi
Agama, meskipun dianggap berakar dari term āgama (Sanskerta) yang berarti tradisi, tapi sepertinya ia lebih dekat dengan terjemahan dari religion (Inggris). Kata ini tidak muncul begitu saja. Wilfred C. Smith dalam The Meaning and End of Religion (1962) mengulas evolusi kata religion. Muasalnya adalah religio yang merujuk pada kekuatan suci atau sikap pada kekuatan tersebut. Hal ini terkait dengan relasi antara manusia dengan dewa. Istilah dewa digunakan untuk memahami entitas yang dianggap adimanusiawi pada masa itu.
Dalam konteks ini, setiap praktik dan tradisi yang terkait dengan itu dianggap religio. Ketika Kristiani berkembang, istilah religio mulai diadopsi. Istilah ini kemudian menjadi semacam penanda identitas yang bermakna cara penyembahan. Tatkala religio diadopsi Kristiani, ia menandakan cara penyembahan yang benar. Konsekuensinya adalah tradisi selain itu dianggap praktik penyembahan yang salah (falsa religio).
Sekitar abad-16, masih menurut Smith, istilah religio bertransformasi sebagaimana dalam karya Calvin Institutio Christianae Religionis (1536) yang bermakna ke-saleh-an. Ke-saleh-an merupakan kata sifat. Karenanya, dibanding dengan kata religion, ia lebih dekat dengan kata religiousness. Baru pada periode kolonialisme abad-17, kata adjektif religiousness berubah menjadi nomina religion. Konteksnya adalah ketika tradisi Kristiani Eropa bertemu dengan tradisi lain di ‘Timur’, maka kata religion digunakan sebagai penanda identitas dengan doktrin yang tegas. Hasilnya adalah religion identik dengan Kristen sebagaimana dipahami saat ini: agama.
Religions
Ketika religion identik dengan Kristen, maka selain tradisi itu dianggap sebagai pagan: penyembah berhala. Istilah ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari politik bahasa Eropa untuk mendefinisikan segala sesuatu di luar Kristen. Intinya adalah Kristen sebagai religion itu benar, sedangkan tradisi selain itu adalah salah.
Masuzawa dalam The Invention of World Religions (2005) melengkapi ulasan itu dengan melihat perkembangan ide tentang religion. Jika awalnya ia singular, maka pada abad-19 ia menjadi plural: religions. Sekali lagi, hal ini terkait dengan perjumpaan antara Kristen dengan berbagai tradisi lain yang mirip seperti Islam, Hindu dan Budha.
Meski para ahli terus berdebat, namun toh pada akhirnya tradisi-tradisi tersebut juga dianggap memenuhi persyaratan sebagai religions. Inilah yang kemudian disebut sebagai agama dunia (world religions). Ide tentang agama dunia ini tetap menjadikan Kristen sebagai prototipe-nya. Karena itu, identifikasi agama selalu berkiblat pada elemen-elemen dalam Kristen seperti doktrin tentang Tuhan, kitab suci, juga ritus.
Jika dalam sejarah agama dunia Kristen menjadi prototipe, maka di Indonesia Islam yang menjadi prototipe. Sedangkan agama-agama yang lain, terang Samsul Maarif dalam Indigenous Religion Paradigm (2019), baru diakui kemudian. Bahkan, Hindu dan Budha ‘pemilik’ kata āgama dalam bahasa Sanskerta belum diakui sampai 1959. Sementara Konghucu baru diakui pada 1965, tapi dua tahun kemudian dilarang dan baru diperbolehkan kembali pada tahun 2001.
Selain Agama
Seolah-olah, transformasi dari religion menjadi religions—baik dalam sejarah agama di dunia maupun dinamika di Indonesia—mengandung ide tentang pluralisme. Gagasan ini seperti mengakomodir ragam tradisi lain. Dengan demikian, ia seperti memberi ruang pada tradisi di luar agama dominan (Kristen dalam sejarah agama dunia dan Islam dalam sejarah Indonesia).
Selain agama, ruang yang tersisa untuk mereka biasanya adalah label seperti pagan, heathen, maupun animis. Secara umum label ini digunakan sebagai identifikasi terhadap penyembahan yang salah. Yaitu segala bentuk tuduhan praktik penyembahan terhadap entitas selain Tuhan yang dianggap benar.
Hakikat penyembahan terhadap Tuhan ini, salah satunya, bisa dilihat dalam studi animisme yang digawangi oleh E. B. Tylor. Di antara karyanya tentang ini bisa dibaca dalam Primitive Culture (1871). Karya ini bukan hanya menyoroti perkembangan agama secara evolusionis, akan tetapi juga secara korelatif digunakan untuk melihat peradaban manusia.
Secara ringkas, agama dianggap bermula dari animisme yang berkembang di masyarakat yang liar. Ia kemudian bertransformasi menjadi politeisme pada masyarakat barbar. Dan akhirnya, berujung menjadi monoteisme pada masyarakat yang beradab.
Animisme dipahami sebagai keyakinan pada roh-roh yang bersemayam di alam seperti batu, pohon, sungai, laut dst. Evolusi kepercayaan ini mewujud dalam personifikasi dari roh-roh tersebut menjadi dewa-dewa. Dalam tata pikir Eropa sentris, puncak evolusi agama tersebut adalah monoteis yang sekaligus mencirikan manusia yang beradab.
Penjelasan agama model Tylorian tersebut selain bersifat evolusionis juga universal. Ia memberikan legitimasi moral-akademis terhadap Kristenisasi seturut proses kolonialisme. Dengannya, kolonialisme tidak semata dipahami sebagai penundukan, penguasaan, dan penjajahan, tapi juga dipahami sebagai proyek pemberadaban.
Ruang Sisa: Budaya
Jika kembali merujuk pada pendapat Smith, pada awalnya semua tradisi adalah religio dalam makna religiousness (religius). Namun ketika identifikasi dalam kerangka pikir agama dunia itu direifikasi (menjadi religion), maka tradisi di luar itu tidak diakui sebagai agama. Konsekuensinya, ruang yang tersisa bagi tradisi selain itu adalah budaya.
Agama dianggap sebagai urusan manusia dengan Tuhan sebagai konsekuensi dari esensialisasi terhadap elemen teologis. Cara berelasi dengan Tuhan kemudian dipahami dalam format ritus yang sangat spesifik. Bukan hanya itu, ritus juga harus mendapatkan legitimasi tekstual dari kitab suci.
Padahal, selain agama dalam standar elemen-elemen tersebut, ada banyak praktik religius lain. Dalam diskursus studi agama kontemporer, praktik tersebut banyak dibahas melalui gagasan tentang epistemologi relasional misalnya oleh Bird-David dalam Animism Revisited (1999). Sementara Irving Hallowel membahasnya dalam kerangka ide personhood.
Pandangan ini memperluas makna person tidak hanya pada manusia (human person), tapi juga pada alam (non-human person). Gagasan ini tidak memandang alam sebagai obyek, tetapi sebagai subyek. Karena itu, hubungan antara manusia dengan alam tidak bisa semata dilihat sebagai relasi subyek-obyek, tetapi sebagai relasi inter-subyektif.
Secara ringkas, agama dianggap bermula dari animisme yang berkembang di masyarakat yang liar. Ia kemudian bertransformasi menjadi politeisme pada masyarakat barbar. Dan akhirnya, berujung menjadi monoteisme pada masyarakat yang beradab.
Dalam kerangka agama dunia seperti teori animisme Tylor, tampak ia mengamini total dualisme Cartesian. Rasionalitas modern Eropa sentris ini menempatkan manusia sebagai subyek (thinking), sementara alam dipandang sebagai obyek (thing). Padahal, banyak masyarakat lokal yang tidak memiliki pandangan dunia seperti ini.
Di bagian akhir, saya ingin mengajukan satu contoh, misalnya larung sesaji. Dalam kerangka animisme, praktik ini seolah-olah manusia memberikan sesaji pada laut. Namun karena praktik ini tidak bisa diterima oleh rasionalitas Eropa, ia kemudian dipersepsi sebagai pemberian sesaji pada figur supranatural penunggu laut (Ratu Kidul). Dengan demikian, ia bisa disebut sebagai animis.
Kalaupun ditengarai ada unsur penyembahan, tetapi Ratu Kidul tidak diterima sebagai bagian dari elemen teologis yang benar. Karena itu, penyembahannya dianggap salah. Secara teologis, kesalahan ini disebut sebagai syirik.
Namun praktik ini tidak dipahami demikian oleh para praktisinya. Para pelaku larung, memiliki cara pandang yang berbeda atas laut. Laut tidak semata-mata dipahami sebagai obyek. Laut adalah subyek yang juga memiliki kapasitas untuk berlasi dengan manusia. Relasi ini bisa baik (memberikan hasil seperti ikan dan seterusnya) sekaligus buruk (memberikan ‘bencana’ seperti tsunami).
Karena relasi yang bersifat relatif itulah, maka setiap subyek perlu melakukan upaya untuk menjaga situasi tetap harmonis. Upaya ini oleh masyarakat diartikulasikan melalui praktik larung sesaji. Praktik ini berjangkar pada pandangan atas definisi subyek yang melampaui rasionalitas modern ala Eropa.
Namun karena begitu hegemoniknya pandangan agama dunia, maka praktik religius seperti itu tidak diakui sebagai agama. Alih-alih melihatnya sebagai praktik religius, ia seringkali dipahami sebagai budaya.
Meski demikian, ia juga tidak bisa dipisahkan total dari agama. Karenanya, tidak jarang praktik-praktik religius yang demikian itu diilhami oleh nilai-nilai agama seperti: ekspresi syukur pada Tuhan. Sayangnya, esensi semacam ini tetap meng-ejawantah-kan elemen teologis yang khas cara pandang agama dunia.
Akhirnya, banyak praktik religius yang ‘dipaksa’ ditempatkan di ruang sisa: budaya. Mungkin, ini bisa saja diterima sebagai strategi agar praktik-praktik tersebut tidak musnah begitu saja. Bukankah dianggap ‘budaya’ masih sedikit lebih baik daripada dituduh praktik syirik, sesat dan semacamnya? Tetapi, tentu saja, ‘advokasi’ untuk mengembalikan ‘budaya’ sebagai ‘agama’ adalah sebaik-baiknya usaha. [ ]