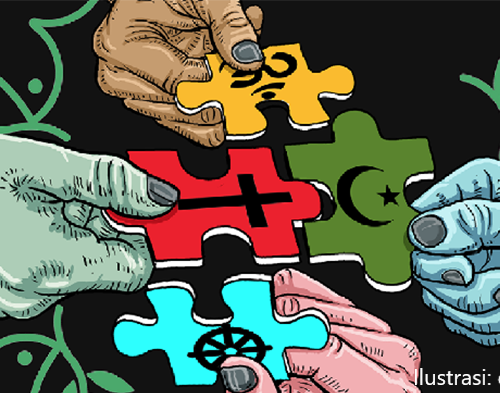Kata “hijrah” kini dan telah menjadi istilah baku dalam mendefinisikan adanya peningkatan kualitas keimanan maupun kesalehan individu dalam kehidupan. Hal ini terlihat dari adanya intensitas untuk memahami dan mendalami ajaran agama dalam relasinya kepada Tuhan maupun relasi sesama manusia.
Perilaku ini sebagian besar banyak dilakukan oleh kalangan kelas menengah Muslim; kelompok masyarakat mapan, dan juga berpendidikan yang berupaya memenuhi dimensi spiritualnya setelah aspek materialnya terpenuhi.
Meskipun demikian, pemaknaan dan pengalaman hijrah di kalangan kelas menengah Muslim tersebut kemudian mengalami banyak perdebatan. Poin utama yang didebatkan adalah motif dan latar belakang seseorang itu mau berhijrah. Mereka dianggap belum sepenuhnya hijrah atas dasar murni panggilan nurani dan agama.
Ada faktor lain semisal untuk mencari pengakuan, faktor pertemanan, dan mungkin faktor panjat sosial yang sekiranya melatarbelakangi orang kemudian mau berhijrah. Tulisan sederhana ini berusaha merangkai alasan kenapa hijrah itu penting di kalangan kelas menengah Muslim Indonesia.
Hijrah sendiri secara etimologis bermakna “berpindah”. Hal ini merujuk pada pengalaman berpindahnya Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dari Mekkah menuju Madinah pada saat malam hari (Hamudy and Hamudy 2020). Dalam sejarahnya, Nabi dan para sahabat sempat bersembunyi di Gua Tsur untuk menghindari kejaran pasukan suku Quraish untuk kemudian sesudahnya melanjutkan perjalanan kembali menuju Madinah.
Adapun secara teologis, makna hijrah sebagai “berpindah” ini memiliki berbagai macam multiintepretasi dalam teks Al-Qur’an misalnya QS al-Ankabut (29:26) yang menerangkan kembali pada pangakuan Tuhan sebagai sebaik-baiknya tempat kembali dan berpindah, QS al-Muzammil (73:10) yakni meninggalkan mereka yang tercela dengan cara baik, dan QS al-Muddatstsir (74:5) yakni meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran (Abbas and Qudsy 2019).
Dengan demikian, secara singkat, hijrah sendiri idealnya dimaknai sebagai perjalanan/perbaikan spiritual seorang individu yang dilakukan secara rahasia dan sembunyi guna menjadi insan yang lebih baik secara religius maupun sosial.
Kemunculan kembali kelas menengah Muslim Indonesia kontemporer juga menandai adanya pergeseran posisi Islam di Indonesia. Sebelumnya di awal abad hingga pertengahan abad 20, Islam berkembang menjadi Islam politik yang tujuannya mengarah pada akses kekuasaan (Jati, 2017).
Kemudian hal itu bergeser pada islamisasi yakni Islam yang berkembang sebagai agama sipil dimana nilai dan ajarannya dianggap sebagai norma sosial yang diterima luas (Machmudi 2008; van Bruinessen 2013; Menchik 2016). Hal ini yang mengakibatkan tuntutan menjadi saleh dan alim menjadi arus utama dalam masyarakat Indonesia saat ini.
Secara lebih spesifik, pengarustamaan Islam sebagai wacana dominan telah terinstitusi dalam berbagai kehidupan. Kondisi tersebut kemudian pada akhirnya membuat posisi kelas menengah Muslim yang secara demografis didominasi kalangan milenial dan Generasi Z dalam posisi galau dalam beragama.
Setidaknya terdapat dua temuan survei menarik yang menangkap kegalauan beragama, yakni dari PPIM UIN Jakarta dan Survei Indikator Politik Indonesia. Survei pertama, anak muda dengan berlatar belakang kelas menengah Muslim cenderung intoleran terhadap pandangan Islam yang berbeda dengan pandangan Islam yang mereka telah yakini sebelumnya (Syafruddin and Ropi 2018).
Hal itu terjadi lantaran ajaran Islam yang mereka dapatkan lebih banyak didominasi dari konten daring ketimbang pengajaran lewat pesantren (Syafruddin and Ropi 2018). Kondisi tersebut kemudian (terkadang) menciptakan disinformasi maupun misinformasi mengenai Islam yang mengakibatkan perilaku/pandangan intoleran dan eksklusif.
Pada survei kedua, anak muda dengan latar belakang kelas menengah Muslim juga cenderung galau soal apakah Indonesia harus diperintah lewat syariah Islam maupun Islam sebagai agama mayoritas harus mendapatkan keistimewaan (Indikator Politik Indonesia 2021). Kegalauan ini salah satunya didasari pada kuatnya agama sebagai referensi utama dalam pengambilan keputusan dalam hidup (Indikator Politik Indonesia 2021).
Hijrah sendiri idealnya dimaknai sebagai perjalanan/perbaikan spiritual seorang individu yang dilakukan secara rahasia dan sembunyi guna menjadi insan yang lebih baik secara religius maupun sosial.
Dengan mengacu pada dua hasil survei di atas, pemaknaan dan pengamalan hijrah bagi kelas menengah Muslim Indonesia sendiri lebih didominasi oleh dorongan atas solidaritas internal berbasis kesamaan pandangan tentang Islam, dan juga motif islamisme awal untuk mengamalkan nilai-nilai Islam dalam ranah politik. Dengan kata lain, hijrah bisa dimaknai sebagai ekspresi eksklusivitas agama, dan sarana sosialisasi bagi kalangan kelas menengah Muslim Indonesia sehingga tidak galau lagi ketika berinteraksi.
Berbagai studi kekinian mengenai fenomena hijrah di kalangan kelas menengah Muslim Indonesia setidaknya menunjukkan dua pola sebelumnya. Kelompok studi pertama yang fokus pada hijrah sebagai media sosialisasi kelas menengah Muslim Indonesia tergambar pada temuan dari Sunesti dkk (2018) dan Farchan serta Rosharlianti (2021).
Hal menarik dari studi pertama itu adalah peran penting konsep Islam ala Salafi yang sebenarnya (kaffah) digunakan untuk menarik atensi kelas menengah Muslim untuk menjadi kelompok yang terselamatkan (the saved ones) di dunia maupun akhirat (Sunesti, Hasan, and Azca 2018). Motif ini menawarkan hijrah dengan cara membuat batasan sosial dengan kaum non-hijrah.
Persepsi ini sebenarnya mengambil insipirasi ketika Nabi Muhammad bersembunyi di gua ketika dikepung oleh Suku Quraish saat berhijrah. Namun demikian, hijrahnya nabi tidak menjadi eksklusif sementara hijrah ala Salafi sendiri berupaya membuat batasan sosial.
Temuan kedua dari Farchan dan Rosharlianti (2021) yang berhasil memotret fakta eksklusivitas agama dalam sisi hijrah. Indikatornya dilihat dari menguatnya daya konsumsi atas barang/jasa yang berlabel “islami” untuk memperkuat citra hijrah di ruang publik (Farchan and Rosharlianti 2021).
Dengan demikian, pada perspektif eksklusivitas agama ini melihat hijrah justru menciptakan “masyarakat baru” dalam sistem sosial yang sudah eksis dengan menciptakan dan mengonsumsi barang/jasanya sendiri.
Sudut pandang kedua hijrah sebagai ajang sosialisasi lebih menitikberatkan motif berhijrah sebagai sarana panjat sosial bagi kelas menengah Muslim ini. Dua studi terkini yang memotret hal itu terutama dari Annisa (2018) dan Hamudy (2020). Studi pertama melihat motif individu untuk berhijrah karena mengejar posisi sebagai selebritis mikro (micro celebrities) dalam masyarakat dengan berupaya menjadikan diri sebagai bagian dari ikon Muslim lewat narasi-narasi konten media sosial (Annisa 2018).
Motif menjadi selebritis mikro (micro celebrities) tentu ada kaitannya dengan islamisasi yang menggejala di masyarakat sehingga aktor hijrah ingin mendapatkan tempat (positioning) dalam arus itu. Senada dengan Annisa, studi Hamudy juga melihat perilaku hijrah lebih banyak didorong adanya spiritualisme digital, yakni pengaruh dari tokoh figur publik yang “berhijrah” dengan menonjolkan sisi kealiman dan kesalehan, misalnya memakai jilbab yang lebih lebar bagi wanita, memelihara jenggot bagi pria, maupun penggunaan diksi Bahasa Arab dalam percakapan popular (Hamudy and Hamudy 2020).
Selain itu pula, hijrah sebagai panjat sosial dimaknai pula sebagai ekspresi kesalehan instan dan komunal dimana individu mapun kolektif yang berhijrah lebih condong karena tidak mau tertinggal dengan tren sosial yang berkembang utamanya dari media. Hal itu yang kemudian menciptakan label dan stigma “hijrah” dan “non-hijrah” dimana yang hijrah ini diterima lebih luas karena konstruksi simbolis tentang saleh dan alim di mata publik.
Dengan demikian—secara garis besar—fenomena hijrah di kalangan kelas menengah Muslim sendiri lebih didorong untuk mencari eksistensi daripada pendalaman substansi agama secara spiritual. Hal ini tentunya kontras dan tidak menemukan korelasinya dengan spirit hijrah Nabi Muhammad SAW maupun teks dalam Qur’an.
Kedua sumber tersebut melihat hijrah sendiri adalah “proses berpindah namun tidak harus menjadi eksklusif dan pusat perhatian.” Hal ini mengingat hijrah sendiri lebih condong pada introspeksi diri untuk menjadi lebih baik daripada mencari rekognisi agar dianggap telah jadi baik. Dengan kembali memaknai secara komprehensif, dan konstektual mengenai makna hijrah itu, kelas menengah Muslim seyogianya tidak lagi terjebak pada citra dan tabiat yang menganggap dirinya paling islami dan kaffah dalam beragama. []